 SEPOTONG kegembiraan kudapat siang ini. Seorang tukang pos memberiku satu bungkus amplop coklat berkop Gramedia. Amplop ini berisi novel terbarunya pengarang Brazil Paulo Coelho. Judulnya adalah The Zahir. Selain novel terjemahan ini ditempeli stiker autographed copy dari penerbit, di halaman depan ada tanda tangan sang pengarang yang tergores dengan tinta hitam.
SEPOTONG kegembiraan kudapat siang ini. Seorang tukang pos memberiku satu bungkus amplop coklat berkop Gramedia. Amplop ini berisi novel terbarunya pengarang Brazil Paulo Coelho. Judulnya adalah The Zahir. Selain novel terjemahan ini ditempeli stiker autographed copy dari penerbit, di halaman depan ada tanda tangan sang pengarang yang tergores dengan tinta hitam.
Dua hari sebelumnya, seorang perempuan dari Palmerah membunyikan ponselku. Memecah kesibukan siangku menulis artikel. Ia mengabari bahwa diriku terpilih menjadi salah satu komentator terbaik atas novel-novelnya Paulo Coelho yang dipamerkan dalam Gramedia Book Fair di Bentara Budaya Jakarta beberapa hari lalu. Berita ini jelas menyenangkan. Paling tidak, aku mendapat satu buku yang bisa menambah riuh perpustakaan pribadiku. Lebih-lebih mendapat tanda-tangan asli dari si penulis novel Sang Alkemis, Veronika Memutuskan Mati, Di Tepi Sungai Piedra Aku Duduk dan Tersedu, dan lainnya.
Berikut sinopsis buku The Zahir seperti yang tertulis di sampul belakang:
Seorang suami ditinggalkan istrinya tanpa alasan, tanpa jejak. Kepergiannya menimbulkan pertany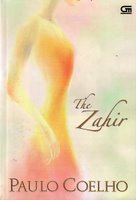 aan besar yang makin lama makin menggerogoti hati dan pikiran, kenangan yang ditinggalkannya tak terhapuskan, hingga obsesi yang nyaris membawa sang suami pada kegilaan.
aan besar yang makin lama makin menggerogoti hati dan pikiran, kenangan yang ditinggalkannya tak terhapuskan, hingga obsesi yang nyaris membawa sang suami pada kegilaan.
Untuk menjawab pertanyaan ‘mengapa’, sang suami menelusuri kembali jejak kebersamaannya dengan sang istri, hal-hal yang terjadi dalam perkawinan mereka, hingga terjadinya perpisahan itu. Pencarian ini membawanya keluar dari dunianya yang aman tenteram ke jalur yang tidak dikenalnya dan membukakan matanya tentang makna cinta serta kekuatan takdir.
read more...
Thursday, August 31, 2006
Tanda Tangan Paulo Coelho
Monday, August 28, 2006
Dari Pramoedya

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah...Menulis adalah bekerja untuk keabadian.”
(Pramoedya Ananta Toer dalam Kotbah dari Jalan Hidup)
Thursday, August 24, 2006
Surga di Ujung Utara Republik (I)
PESAWAT Lion Air dengan nomer penerbangan JT 776
itu mendarat selamat di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Lega rasanya setelah dua jam melintasi langit. Kamis itu masih pagi, 29 Juni 2006. Langkah pertamaku saat menginjakan kaki di tanah penghasil kue halua kenari itu adalah mencocokkan jam digital di ponselku dengan waktu setempat. Pasalnya, Manado lebih awal satu jam ketimbang Jakarta.
Di pojok langit bandara, Gunung Klabat sudah menunggu. Gunung yang kata orang setempat berisi air di bagian kawahnya itu menjulang tenang. Pagi itu, pucuk gunung itu tertutup lembaran awan putih. Tampak anggun bak lukisan di atas kanvas.
Tanah Manado adalah gerbang perdana rute perjalananku menuju Talaud, sebuah kabupaten termuda di ujung utara Indonesia. Aku diserahi tugas untuk meliput kabupaten Talaud di hari ulang tahunnya yang ke-4. Talaud merupakan kabupaten pemekaran dari Sangihe-Talaud. Karena Talaud merupakan daerah kepulauan, transportasi didominasi oleh jalur laut. Lika-liku panjang harus aku lalui.
Bersama seorang kawan, aku mengambil jeda dengan menyerutup secangkir capuccino di kounter minuman bandara. Harian Manado Post dengan harga eceran Rp 3000 sejenak menemani kami. Sudah menjadi ritual lama membeli koran setempat bila aku berpergian jauh. Tidak lama, seorang bercelana tanggung, berkaos putih, bertopi biru, mendatangi kami. Ia menawarkan jasa angkutan. Kami pun terlibat dalam negosiasi harga. Setelah sepakat, segera kami berkemas. Mobil kijang merah segera membawa kami menuju pelabuhan. Jarak bandara dengan pelabuhan Manado sekitar 15 kilometer. Kami pun harus merogoh kocek sebesar Rp 70 ribu, sesuai kesepakatan.
Perjalanan menuju pelabuhan cukup mengasyikan. Selain karena keramahan si sopir yang mengaku bernama Frans, juga hal-hal mencolok di jalanan. Bangunan gereja bertebaran di sepanjang jalan. Bisa jadi, satu kilometer perjalanan, aku bisa menghitung ada sekitar tujuh gedung gereja berdiri di pinggir jalan. Maklum, mayoritas penduduk Sulawesi Utara adalah Kristen. Inilah jejak nyata dari para misionaris Spanyol yang ikut mewartakan Kabar Baik bersama para musafir di abad ke-16.
Hal mencolok kedua adalah bendera dan umbul-umbul Piala Dunia 2006 berkibar di hampir setiap rumah. Atribut-atribut tim-tim di putaran final pun dipasang di banyak angkutan yang beradu jalan dengan kijang kami. Beda dengan Jakarta, sepi. Kata Frans, tidak hanya itu. Mereka juga melakukan pawai di jalan-jalan, tak mau kalah dengan kampanye saat Pilkada. Bahkan, ajang olah raga bergengsi ini menjadi bahan judi dan taruhan. Tak hanya uang yang dipertaruhkan, tapi juga tanah, rumah, dan mobil.
Setelah kurang lebih setengah jam, kijang merah itu berhenti. Tepat di depan gardu masuk pelabuhan. Angin pantai mulai menyapu tubuh. Suara hiruk-pikuk orang di pelabuhan menjadikan pagi menjelang siang menjadi riuh. Segera lima orang berlarian menjemput kami. Mereka menawarkan angkutan kapal motor berukuran kecil. Tapi, sesuai saran, aku harus naik kapal besar. Pasalnya, perjalanan ke Talaud lebih aman dengan kapal besar. Diantar Frans, aku pun menuju kounter karcis kapal. Akhirnya, setelah keliling, aku mendapatkan tiket kapal Maria Ratu seharga Rp 150 ribu. Untuk menyamankan perjalanan selama 18 jam itu, kami memesan kamar seharga Rp 300 ribu.
Nama-nama kapal yang merapat di pelabuhan sangat bernuansa Kristen. Sebut saja Maria Ratu, Queen Mary, Elisabet, Margaret, Ave Maria, dan sebagainya. Bahkan, di ruang radio dan nahkoda, tertata perabot religius seperti salib, patung Maria, patung Yesus. Tak jarang pula, sering terdengar teriakan ‘aleluya’ dari kerumunan orang di pelabuhan. Tak jelas, apakah mereka sedang memuji Tuhan atau mengumpat.
Setelah tiket ada di tangan, aku segera menunggu di pos pelabuhan. Menurut jadwal di tiket, aku harus menunggu tiga jam untuk bisa naik kapal. Di pos, orang berkerumun menunggu kapal. Tak lama, perutku mulai mengeluarkan suara manja. Pertanda harus diisi makanan. Mataku menyapu pos, mencari warung makan. Di pojok, ada warung makan. Aku pun makan nasi kuning dengan lauk telur goreng dan sambal udang yang pedasnya menusuk langit-langit mulut.
Setelah makan, aku pun berjalan-jalan santai di pesisir pelabuhan. Kamera digital keluaran Pentax terkalung di leher. Angin pantai bercampur bau pasir membangkitkan adrenalinku untuk berpetualang. Mataku menjelah dari sudut ke sudut pelabuhan. Perumahan dengan genting warna-warni membuat suasana pesisir jadi indah. Bangunan kantor pelabuhan dengan tembok bercat warna-warni menjulang dengan gagah. Pelabuhan Manado tampak cukup bersih dan tertata. Minimal lebih baik ketimbang pesisir Muara Angke Jakarta yang aku sambangi tahun lalu.
Wajah pelabuhan ini tentu saja sangat berbeda dibanding saat kapal-kapal musafir Spanyol pimpinan Ferdinand Magelhaens merapat pada 1532. Menurut data sejarah, pelabuhan ini pernah dijadikan persinggahan dan posko perolehan air tawar sebelum Spanyol menguasai kepulauan Filipina pada 1542. Relasi para musafir Spanyol dan penduduk setempat terjalin erat dalam sektor ekonomi. Mereka melakukan barter beras, damar, madu, dan hasil hutan dengan ikan dan garam. Lantaran cuaca tropisnya, Spanyol pernah menjadikan Manado tempat yang tepat untuk membuka perkebunan kopi. Biji kopi di dapat dari Amerika Selatan dan hasilnya di pasarkan di daratan Cina.
Dua setengah jam berlalu. Tampak orang semakin berjubel masuk kapal. Segera aku membawa tas ranselku dan ikutan rombongan masuk Maria Ratu. Setelah berdesakan dengan para buruh pelabuhan memasukan barang, akhirnya aku sampai di tingkat II. Kamar nomer 5 sudah terbuka. Aku menaruh tas di kamar itu. Hampir empat jam aku harus menunggu di geladak kapal. Jadwal yang tertera di tiket tidak berlaku. Para buruh sibuk mengangkat barang ke kapal. Ada kasur, sepeda motor, kursi, meja, botol-botol softdrink, indomie, dus-dus komputer, dan sebagainya. Barang-barang ini mau dibawa ke Talaud. Maklum kebanyakan barang di Talaud dibeli dari Manado.
sepeda motor, kursi, meja, botol-botol softdrink, indomie, dus-dus komputer, dan sebagainya. Barang-barang ini mau dibawa ke Talaud. Maklum kebanyakan barang di Talaud dibeli dari Manado.
Mulai jenuh menunggu, aku pun bertanya pada salah seorang penumpang tentang keberangkatan kapal ini. “Biasanya jam enam mas, nunggu air laut pasang dulu,” katanya sambil telunjukknya mengarah pada permukaan air laut. Mau tidak mau, aku memilih sabar. (bersambung).
read more...
Wednesday, August 23, 2006
Sekeping Mata Cinta
 AKU masih duduk termangu pada tepian malam. Masih kuingat kejadian di sebuah resto cepat saji di bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Di sana ada obrolan. Di sana ada cerita. Di sana ada cinta. Gadis berambut ikal bermata tajam itu terus memandangiku. Kubalas tatapannya dengan mataku yang merangsek ke relung mata hatinya. Suara air kolam dan sajian fried chicken menemani obrolan kami. Sementara beberapa remaja kota asyik bersenda gurau dengan logat khas Jakartanya. Tapi, suara-suara itu tidak mengusik konsentrasi kami dalam topik pembicaraan.
AKU masih duduk termangu pada tepian malam. Masih kuingat kejadian di sebuah resto cepat saji di bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Di sana ada obrolan. Di sana ada cerita. Di sana ada cinta. Gadis berambut ikal bermata tajam itu terus memandangiku. Kubalas tatapannya dengan mataku yang merangsek ke relung mata hatinya. Suara air kolam dan sajian fried chicken menemani obrolan kami. Sementara beberapa remaja kota asyik bersenda gurau dengan logat khas Jakartanya. Tapi, suara-suara itu tidak mengusik konsentrasi kami dalam topik pembicaraan.
“Apa kamu yakin kita mampu menikah,” tanya gadis rambut ikal itu. Aku menangkap sekelebat keraguan muncul dalam relung matanya yang tajam. Kutarik dua tangannya di atas meja. Kugegam erat dengan penuh semangat dan dengan asa tiada bertepi. Pelan kubuka mulutku dan kubisikan padanya, “Aku yakin, tidak usah takut.”
Menikah adalah keputusan yang tidak sepele. Bukan main-main dan tidak boleh dipermainkan. Keraguan yang aku tangkap dalam bola matanya itu, mengingatkanku akan cerita dari Sang Guru, seorang Guru yang diamini hampir semiliar warga bumi ini. Sang Guru itu pernah bercerita tentang seorang raja yang hendak maju berperang. Adalah bijak, jika raja itu duduk termangu untuk menimbang-nimbang seberapa kekuatan musuh dan seberapa kekuatan skuad tentaranya. Ini untuk mengantisipasi rasa malu jika pasukannya kalah dan raja itu pulang kandang dengan pakaian lusuh dan jiwa yang hancur karena kekalahan. Demikian juga dengan pernikahan. Ia membutuhkan pertimbangan yang bijaksana. Dan keraguan gadis berambut ikal itu cukup lumrah. Realistis.
Aku kembali duduk di atas singgasana pikiranku. Aku melihat diriku dalam sebuah cermin. Aku mulai berpikir, dan karena itu aku ada. Berpikir atau ragu-ragu bedanya cukup tipis. Tapi, aku memilih kata berpikir karena keraguan sudah ada dalam bola mata gadis berambut ikal itu. Apakah aku mampu mengadakan sebuah perhelatan cinta yang sekali seumur hidup menurut Gereja Katolik itu?
Aku sadar diriku hanyalah seorang perangkai dan penjual kata-kata. Upah dalam merangkai kata-kata itu pun tidak seberapa. Tapi asa dalam diriku tidak pernah berkesudahan. Asa itulah yang menjadi bara energi hidupku melintasi rimba raya kehidupan yang penuh misteri ini. Asa itulah yang menyibak segala problematika dan seribu satu keraguan: mau makan apa, tinggal di mana, kalau ada musibah bagaimana, dan sebagainya.
Kutatap lagi gadis berambut ikal itu lagi. Rasanya ingin kupersilakan bola matanya itu membaca apa saja yang tertulis dalam hatiku saat itu. Pelan aku membuka bibirku dan mengatakan, “Jangan takut. Yakin saja. Di mana ada cinta, di situ pasti ada jalan.”
Aku terhenyak. Demikian juga gadis berambut ikal itu. Aku tak percaya aku bisa mengucapkan kata-kata itu. Rasanya ini sebuah aufklarung, fajar budi, pencerahan. Bak Archimedes yang tercebur di dalam bak air, aku berteriak eureka, aku telah menemukannya. Sebuah cinta, sebuah jalan. Di mana ada cinta, di situ ada jalan. Ah, ini laksana iringan The Magic Flute karya Wolfgang Amadeus Mozart. Iringan pembebasan orang-orang yang ingin merdeka dari rasa ketakutan, dogmatisme, dan kekerdilan berpikir di Abad Pertengahan. Sang Surya telah terbit menghalau kegelapan.
Bola mataku bertatapan dengan bola matanya. Aku melihat sebuah pelita kecil mulai menyala dalam matanya. Redup. Tapi ia tetap memilih mengunci bibirnya yang ranum.
Percikan aufklarung tadi mengantar memoriku pada seorang bocah penggembala di padang rumput Andalusia. Ia bernama Santiago. Santiago adalah tokoh rekaan Paulo Coelho, seorang novelis berdarah Brazil. Santiago aku temukan dalam novelnya berjudul Sang Alkemis. Novel ini pula yang menjadi kadoku buat gadis berambut ikal itu di malam Natal tahun lalu. Novel ini berkisah tentang pencapaian mimpi Santiago. Mimpi yang harus dibayar dengan peziarahan panjang dan melelahkan.
Perjumpaan dengan seorang tua bernama Melkizedek menyadarkan Santiago itu pada Legenda Pribadi. Setiap orang mempunyai Legenda Pribadi masing-masing. Tapi, Raja Salem itu mengingatkan, banyak orang yang gagal mewujudkan Legenda Pribadinya itu. Banyak orang yang rela menyerahkan hidupnya pada nasib. Orang tidak punya keyakinan, orang takut, orang tidak punya kehendak yang kuat, dan orang kehilangan mimpinya itu. Lebih parah lagi, orang tidak berani bermimpi.
Santiago percaya kalau dirinya yakin mimpinya, maka seluruh alam semesta ini akan membantu meraihnya. Orang Jawa pernah berpesan, rezeki bagi orang menikah tidak usah dikawatirkan. Satu mulut, rezekinya datang mencukupi buat satu mulut. Ketika menikah, ada dua mulut. Maka alam akan memberikan rezeki itu secukup dan seadilnya. Itulah kebijaksanaan alam.
Kaki Santiago berlanjut melangkahi Tangier, sebuah kota pelabuhan di Afrika. Perjalanan berlanjut ke padang gurun Arab. Di sana ia bertemu dengan Sang Alkemis, Batu Filsuf, dan Obat Hidup. Di oasis Al-Fayoum, ia bertemu dengan seorang gadis dan jatuh cinta. Namanya Fatima. Segera adegan ala Katakan Cinta, sebuah program komersial salah satu televisi swasta, terjadi. Balasan Fatima menghentak jantung Santiago. “Seorang dicintai karena ia dicintai. Tak perlu ada alasan untuk mencintai,” kata Fatima.
Perjumpaan dengan Sang Alkemis menjadi batere peziarahan meraih mimpi Santiago. “Hanya satu hal yang membuat kamu meraih mimpi kamu,yakni keberanian. Memang menakutkan dalam mengejar mimpi-mimpi itu. Kamu mungkin akan kehilangan semua hal yang telah kau dapatkan,” kata Alkemis.
Memang, ketakutan adalah modal bagi setiap pecundang. Ketakutan adalah wajah awal dari sebuah kegagalan. Persis juga yang diucapkan Miyamoto Musashi, pangeran pedang Jepang rekaan novelis Eiji Yoshikawa, “Aku diajari untuk tidak takut pada siapa pun. Hanya satu yang saya takuti, yakni ketakutan itu sendiri.”
Aku tidak mau jadi pecundang. Kugenggam lagi tangannya. “Yank, mau kan meraih mimpi-mimpi kita. Tapi, semua tetap bebas dan merdeka. Kamu tetap merdeka untuk menentukan pilihan, sebelum semuanya terlambat,” kataku pada gadis berambut ikal itu. “Ya, aku mau sama kamu. Tapi, apa yang sudah kita punyai,” ia menyahut dan menyembulkan secuil keraguan.
“Ya, untuk saat ini aku tidak mempunyai banyak. Mungkin orang lain bisa menyediakan banyak hal untukmu. Tapi, aku sekarang seperti seorang janda miskin yang mempersembahkan satu keping mata uang di Bait Allah. Mungkin, ia satu-satunya orang yang memberi paling sedikit, cuma satu keping mata uang. Yang lain memberi berkeping-keping. Tapi, jangan kira dia tidak memberi apa-apa. Justru, dia yang memberi paling banyak dari orang lain itu. Sekeping mata uang itu adalah seluruh hidupnya. Banyak orang yang memberikan banyak keping dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Bahkan, seluruh hidupnya ia serahkan,” kataku lirih.
Bola mata gadis berambut ikal itu mulai basah. Tergenang air mata. Meluber dan mengalir deras melalui kedua pipinya. Gadis itu menangis. Ia menggegam erat tanganku. Bibir ranumnya sedikit bergetar. Ia berancang-ancang mengucap sesuatu. Dan...”Aku sayang dan pilih kamu. Kita pulang sekarang,” katanya.
Bibirku terkunci. Terdiam untuk beberapa lama, sampai sepeda motorku melaju meninggalkan Kemang dengan sekeping mata cinta.
Adegan itu berakhir. Aku tersadar kembali dari permenunganku. Malam masih berselimutkan kesunyian. Aku mulai beranjak. Di ruang tamu kulihat ibuku sedang membaca majalah tempat tulisan-tulisanku diterbitkan. Ibuku pernah bilang, “Jangan menjadi orang yang seperti tidak mempunyai Tuhan.” Kata-katanya tajam dan menusuk alam kesadaranku. Aku pun berlenggang dan melanjutkan malam itu dengan menonton bola, Inggris melawan Paraguay.
@ artikel ini diterbitkan di buku kenangan pernikahan Thomas&Sara 3 September 2006 berjudul "Sigaran Nyawa: A Tribute to Love".
read more...
Ada Gie di Diariku

AKU buka-buka laptopku. Malam ini, cukup sepi. Biasa, kesepian sering mampir tiba-tiba di bilik hatiku. Aku sengaja buka folder diari. Sengaja pula aku buka diari di folder tahun 2005. Eh, aku menemukan tulisanku tentang Soe Hok Gie dalam diariku. Berikut aku postingkan:
Selasa, 19 Juli 2005
Hari ini, aku nonton film Gie bersama Femi, temenku seorang wartawan Kontan. Malam itu, bioskop Megaria tidak begitu ramai. Mungkin, karena ini hari kerja bukan weekend. Tiket seharga Rp 20 ribu segera kami beli. Aku sedang serius mengenal sosok Soe Hok Gie baru-baru ini setelah wacana pemikirannya dibuka dengan film. Sekilas aku pernah membaca bukunya yang diterbitkan LP3ES berjudul “Catatan Seorang Demonstran” di Toko Buku Gramedia Taman Anggrek beberapa pekan lalu. Sangat menarik dan inspiratif. Aku sendiri merasa sangat ketinggalan membaca Soe dan pemikirannya. Padahal, buku itu senantiasa hadir di perpusatkaan di setiap asrama tempat aku tinggal.
Tapi, apalah arti ketertinggalan, toh waktu masih memberi ruang bagiku untuk belajar banyak darinya. Tapi, sudah ada nih buku ‘Catatan Seorang Demonstran’ dan ‘Soe Hok Gie: Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani’ karya John Maxwell terbitan Grafiti.
Studio 4 Megaria dipenuhi dengan orangmuda. Tampak beberapa orangtua ikutan nonton film yang disutradarai Riri Reza dan diproduseri Mira Lesmana itu. Semula, aku merasa sayang ketika sosok aktivis dan intelektual muda itu diperankan oleh para bintang popular anak muda sekarang, seperti Nicholas Saputra, Wulan Guritno, dan sebagainya. Muncul sedikit kekawatiran animo orangmuda yang nonton film itu bukan karena sosok Soenya tetapi sosok Nicholas Saputra yang mulai mengorbit sejak main di film garapan anak negeri “Ada Apa Dengan Cinta.” Tampak antre berderet orangmuda dengan wajah-wajah beragam. Ada yang wajah culun dan cool dengan tampang-tampang pengidola Peter Pan. Tapi, ada juga tampang-tampang sangar, sorot mata tajam, dandandan acak-acakan, bak aktivis mahasiswa. Ada kekawatiran juga bila terjadi distorsi sejarah.
Tapi, aku tak lama sadar. Aku melihat kejeniusan Riri Reza dalam hal ini. Dengan menggunakan ikon remaja populer sekarang, Riri mau mengajak orangmuda untuk mempelajari sejarah. Belajar sejarah secara visual, dengan film. Soal sejarah, aku teringat yang diprihatinkan Pramoedya Ananta Toer di saat hari ulangtahunnya ke-80. Pram prihatin tentang sejarah yang tidak diminati kaum muda sekarang. Padahal, menurutnya, Bangsa ini selalu terpuruk dalam lingkaran setan kesengsaraan dan persoalan karena tidak pernah belajar dari sejarah. Nah, Riri tampaknya mau memasukkan pelajaran sejarah dengan metode alternatif, yakni film. Aku membayangkannya Riri mencoba mempertemukan dua generasi, yakni generasi Soe dan generasi Nicholas Saputra. Harapannya, keduanya bisa berdialog dan saling belajar. Lihat saja nanti, apakah ini menjadi awal gerakan orangmuda yang baik? Aku pun berharap demikian...aku lihat positifnya deh!
Ada dua hal dari sosok dari Soe yang menarik bagiku. Pertama, kegigihan dia sebagai seorang intelektual. Kedua, kecintaannya pada menulis sebagai alat pergerakkan. Dari catatan-catatan yang aku baca, film yang aku tonton, dan komentar orang tentang sosok Soe, aku bisa melihat Soe memegang teguh komitmennya sebagai seorang intelektual. Ingat Soe, aku ingat apa yang kubaca dari Julien Benda, khususnya tentang Pengkhianatan Intelektual (La Trahison des Clercs). Aku baca Benda bukan dari buku aslinya, tapi dari bukunya Edward Said berjudul Sang Intelektual. Said cukup banyak menyinggung karya Benda itu.
Nah, aku lihat sosok Soe seperti intelektual yang digambarkan Benda. Dia tidak hanya berteori dan menganalisis bak raja yang duduk di menara gading, tapi Soe juga terjun dalam gerakan dan mengalami lapangan. Soe juga tidak mau jadi partisan. Artinya, ikut dalam partai atau kelompok tertentu tang sarat ragam kepentingan. Ia memilih berjalan sendiri. Seorang diri dan kadang mengalami kesepian.
Sisi kedua yang menarik, yakni Soe senang menulis. Kelihatan sekali, Soe menggunakan media tulisan sebagai alat perjuangan. Jujur, ini yang memberi inspirasi aku yang lagi belajar menulis. Tulisan-tulisan di media massa dan catatan hariannya ternyata sangat berguna. Kritikan-kritikannya memberi semangat pergerakkan. Tapi, banyak juga yang marah, sakit hati, dan tidak suka dengan tulisan-tulisan Soe. Aku paling tersentuh dengan komentar dari Arif Budiman, kakak Soe, tentang kegelisahan Soe atas apa yang selama ini ia kerjakan.
Perasaan Soe itu juga pernah aku alami. Merasakan apa yang kulakukan tidak ada gunanya dan malah membuat banyak orang sakit hati. Tak sedikit orang yang menganggap tulisanku terlalu tajam mengkritik gereja, khususnya parokiku. Terlalu berani, tidak sopan. Tapi, ada juga yang melontarkan apresiasi positif. Kadang, merasa apa yang aku kerjakan aneh-aneh saja dan tidak ada gunanya. Ditambah dengan Kafe Socrates, forum diskusi bulanan. Pernah, aku dibilangin oleh seorang kawan? “Mau mengubah Gereja ya. Mustahil!” katanya. Bahkan, seorang mantan ‘pejabat Gereja’ pernah menganggap Kafe Socrates sebagai tong sampah, bisanya cuma menyalahkan gereja.
Tapi, aku pernah dengar dari pemredku di LeadershipPark. Nara Patrianila namanya. Dia pernah berujar, “Kata adalah mantra. Dan mantra itu berenergi. Energi tidak bisa dimusnahkan. Ia kekal. Ia cuma bisa diubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya...” Aku percaya pada itu bahwa kata adalah mantra. Itu kan pelajaran Fisika. Persis seperti yang dilakukan Soe. Meskipun ia sudah mati dalam pelukan hawa beracun puncak Semeru, tapi Soe masih hadir sekarang dan di sini.Tak percaya, rasakan saja. Makanya, aku terus belajar menulis. Aku beruntung punya sahabat dan komunitas yang peduli pada dunia menulis ini.
Uahhh. Udah mengantuk nih. Sebaiknya, aku tutup malam yang sudah mulai runtuh jadi pagi ini dengan tidur. Kasur dan bantal sudah merangsang untuk aku tiduri. Pengin rasanya cepat ‘bercinta’ dengan mereka. Melihat buku-buku yang terserak di rak samping tempat tidur, aku sempat merasa sayang. Oke deh, akan kusentuh lagi kalian...tapi, aku masih males-malesan kalo besok pagi aku ke kantor. Karena aku lagi males disuruh menulis yang sebenarnya aku males menulisnya. Ha ha ha...Luweh!
Bumi yang Dilukai
 ADA pengalaman menarik yang aku jumpai saat aku menunaikan tugas fasilitator kemping Komisi Kepemudaan Keuskupan Bogor, di Cibodas, saat libur panjang kemarin. Aku sengaja lewat Bandung karena arus lalulintas menuju Bogor macet banget. Saat bus umum jurusan Cianjur-Padalarang melintasi jalanan Cipatat, tampak gunung-gunung kapur sudah mulai meranggas. Gunung yang dikenal gunung Masigit dan berderat dengan gunung-gunung kapur lain sepanjang Tagog Ayu sampai Rajamandala itu sudah hancur.
ADA pengalaman menarik yang aku jumpai saat aku menunaikan tugas fasilitator kemping Komisi Kepemudaan Keuskupan Bogor, di Cibodas, saat libur panjang kemarin. Aku sengaja lewat Bandung karena arus lalulintas menuju Bogor macet banget. Saat bus umum jurusan Cianjur-Padalarang melintasi jalanan Cipatat, tampak gunung-gunung kapur sudah mulai meranggas. Gunung yang dikenal gunung Masigit dan berderat dengan gunung-gunung kapur lain sepanjang Tagog Ayu sampai Rajamandala itu sudah hancur.
Gunung itu seakan terluka. Lukanya menganga lebar dengan warna putih. Punggung bumi itu tergolek tak berdaya. Di sekitar gunung, ada semacam kawasan industri pengerukan dan pengolahan batu kapur. Gunung itu tampal ‘kroak’ (hilang sebagian) dan kelihatan rapuh. Sangat ngeri bila runtuh akibat gempa, hujan, atau kena hantaman angin kencang. Pasti akan membahayakan masyarakat sekitar. Dari udaranya, tampak sekali ada pencemaran lingkungan di sana. Genting-genting rumah penduduk tercemar dengan debu-debu kapur. Berapa persen yang dihirup dan mencemari paru-paru penduduk setempat. Belum lagi dengan terganggunya lahan pertanian penduduk dan berkurangnya sumber mata air.
Gunung kapur itu mengingatkanku pada satu bola keprihatinan yang dilemparkan Gereja, khususnya tentang lingkungan hidup. Aku mencoba belajar memahami kertekaitan iman dengan lingkungan hidup. Relasi iman dengan sampah dan dimensi sosial dari sampah dan lingkungan hidup itu.
Persoalan lingkungan hidup adalah persoalan manusia. Lingkungan hidup adalah ruang manusia bereksistensi (berada dan mengada). Rusaknya lingkungan hidup menjadikan keberadaan manusia terusik sekaligus terancam. Iman sendiri tidak hanya berpola vertikal (pada Tuhan), tetapi juga teraktualisasikan secara horisontal (pada ruang-ruang sosial). Salah satu ruang sosial itu adalah lingkungan hidup.
Aku semakin sadar bahwa proses globalisasi yang terus menderu ini telah meminggirkan banyak pihak. Kesejahteraan bersama yang dikoar-koarkan para penganut ekonomi liberal hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang di muka bumi ini. Globalisasi yang menjadi jubah neoliberalisme (baca: pasar bebas) hanya menjadi motor korporasi-korporasi raksasa untuk memaksimalisasi modal dengan menghalalkan segala cara, termasuk merusak lingkungan. Rusaknya lingkungan berakibat langsung pada masyarakat. Sementara itu, hukum negara masih tampak kurang tegas dan kurang adil terhadap aksi-aksi perusakan lingkungan ini. Dari persoalan lingkungan ini, kita bisa melihat timpangnya relasi tiga poros (negara-pasar-dan masyarakat warga) sebagai penyangga keadaban publik.
Perusakan lingkungan ada di mana-mana. Contoh konkretnya, pembalakan hutan (illegal logging), pencemaran air sungai, polusi pabrik dan kendaraan bermotor, pencemaran air bersih, banjir, persoalan sampah, persoalan lumpur di Sidoarjo, tanah longsor, dan sebagainya. Masih berlanjut dengan penyakit yang muncul karena rusaknya lingkungan seperti demam berdarah, minamata, radang paru, keracunan, dan sebagainya. Selain itu, masyarakat warga semakin susah untuk mengakses udara bersih, air bersih, tanah, kesehatan, karena banyak dimensi publik yang sudah diprivatisasi dan dikuasai oleh korporasi-korporasi besar. Hukum negara lebih berpihak pada para pemilik modal. Kepentingan poros masyarakat sering dikorbankan (bdk. Nota Pastoral 2004).
Aku jadi ingat beberapa poin yang pernah aku tulis dalam skripsiku yang mengacu pada pemikiran Anthony Giddens, terkait dengan lingkungan hidup. Sosiolog Inggris ini mengatakan bahwa alam telah berakhir (the end of nature). Globalisasi telah membunuh alam dan menggantikannya menjadi alam buatan (created environment). Apa maksudnya? Banyak fenomena bencana alam sekarang yang tidak lagi murni datang dari alam, melainkan akibat ulah manusia-manusia modern dengan rasio instrumentalnya. Pemanasan global, banjir, tanah longsor, polusi, efek rumah kaca, penyakit, kelaparan, krisis energi, kekeringan, sekarang tidak murni datang dari alam, melainkan datang akibat ulah manusia. Risiko ekternal dari alam pun sudah berubah menjadi risiko buatan (manufactured risk).
Nah, karena persoalan hidup itu dipicu oleh tindakan manusia dan berdampak pada ruang eksistensi manusia, persoalan hidup ini memunyai dimensi sosialnya.
read more...
Chico Mendez: Bara di Hutan Amazon
 AMAZON pada tahun 1980-an berwarna merah membara. Hutan yang hijau dan rimbun itu mulai tampak gundul karena penebangan hutan yang membabi buta. Ekologi dan ekosistem Amazon gusar dan terancam. Paling tidak, kegusaran ini muncul dalam hati seorang paruh baya berdarah Brazil bernama Chico Mendez. Chico Mendez lahir pada 15 Desember 1944. Ia lahir dan bertumbuh dalam lingkungan keluarga penyadap karet yang dikenal dengan nama seringueiros. Ia tumbuh dalam keluarga miskin dan buta huruf. Chico menjadi penyadap karet pada usia 9 tahun setelah dilarang sekolah.
AMAZON pada tahun 1980-an berwarna merah membara. Hutan yang hijau dan rimbun itu mulai tampak gundul karena penebangan hutan yang membabi buta. Ekologi dan ekosistem Amazon gusar dan terancam. Paling tidak, kegusaran ini muncul dalam hati seorang paruh baya berdarah Brazil bernama Chico Mendez. Chico Mendez lahir pada 15 Desember 1944. Ia lahir dan bertumbuh dalam lingkungan keluarga penyadap karet yang dikenal dengan nama seringueiros. Ia tumbuh dalam keluarga miskin dan buta huruf. Chico menjadi penyadap karet pada usia 9 tahun setelah dilarang sekolah.
Sampai tahun 1970, para juragan kebun karet melarang warga untuk sekolah. Lalu, Chico belajar sendiri dengan fasilitas yang jauh dari memadahi. Pengalaman kemiskinan dan ketertindasan justru mencetak karakter Chico yang pemberani dan solider dengan saudara-saudara senasib di Amazon.Praktik penyadapan getah karet ini pun sudah lama ada dan diturunkan dari generasi ke generasi. Getah karet menjadi tumpuan masyarakat Amazon dalam mengisi ceruk dapurnya. Getah itu bisa diolah menjadi berbagai macam produk, seperti ban kendaraan, penghapus pensil, dan perkakas karet lainnya. Tapi, penebangan liar yang ilegal dan serampangan juga menjadi masalah yang muncul kemudian hari. Ini menjadi sebuah ajang eksploitasi yang sangat membahayakan ekosistem hutan.
Chico Mendez mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang seringueiro.Amazon menjadi sebuah lahan yang menggiurkan untuk mengeruk banyak keuntungan. Banyak uang bisa diperoleh dengan menebang hutan dan mengganti lahanya menjadi tempat potensial untuk membuat pertambangan.Menyadari bahaya yang mulai dialami Amazon, Chico Mendez bangkit untuk meluncurkan berbagai kritikan pada kebijakan pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dinilai membahayakan ekologi. Mendez menjadikan dirinya sebagai sebagai oposisi dari industrialisme dan pejabat pemerintah yang korup dengan mengambil keuntungan dari penebangan hutan. Ia mengumpulkan banyak orang dan menjadi motor penggerak komunitas pencinta hutan di Amazon. Penyadaran atau konsientisasi pada masyarakat Amazon dilakukan.
Mereka mulai melakukan gerakan pencegahan penebangan hutan. Mendez mengorganisasi para petani karet untuk bekerja bersama dalam angka mempertahankan rumah dan lahan mereka sembari mencari dukungan internasional.Pada tahun 1970-an, Chico menjadi seorang pemimpin dalam sebuah gerakan non violence untuk mempertahankan hutan dan rumah meraka dari pengrusakan. Lima tahun kemudian, ia mendirikan Union Movement di Acre. Dia membantu Partai Buruh Kiri pada tahun 1979. Pada tahun 1985, Chico mendirikan Badan Nasional Petani Karet, sebuah organisasi non pemerintah yang bermisikan untuk melindungi dan melestarikan hutan dan perkampungan Amazon.
Dia juga yang mengorganisasi pertemuan nasional perdananya di Brazil dengan dukungan seorang anthropolog, Mary Helena Allegretti. Chico amat getol melawan praktik penebangan liar (illegal logging) demi kelestarian hutan. Tak lama, Chico mendapatkan dua penghargaan internasional, yakni Global 500 Award oleh Komisi PBB untuk lingkungan (UNEP) dan Ted Turner’s Better World Society Environment Award. Dengan bantuan Stephan Schwartzman dari Environmental Defense dan lembaga lain, Chico menjadi dikenal secara internasional sebagai seorang petani karet, pemimpin serikat, dan aktivis akar rumput Brazil.
Mendez bertempur dengan gagah berani melawan praktik penindasan. Jiwa kepemimpinan lelaki kampung ini mampu menggetarkan perusahaan-perusahaan besar yang mengekploitasi hutan. Ia membela sistem perlindungan pertanian dan mendesak para sahabatnya untuk menggunakan cara-cara non kekerasan untuk melawan korporasi yang telah merampok lingkungan hidup mereka. Sikap radikal Mendez dan kawan-kawan tercium pemerintah. Tak lama, berbagai penculikan, penangkapan, bahkan pembunuhan terhadap para aktivis pembela masyarakat Amazon pun terjadi. Teror dan ancaman sering diterima Chico Mendez.
Akhirnya, Mendez berhasil dijebloskan ke dalam penjara, didera dan diancam. Tapi, jeruji penjara dan siksaan tidak membuat Mendez patah arang untuk mewujudkan misi menyelamatkan hutan tercintanya. Pada tahun 1988, seorang tuan tanah bernama Alves de Silva memerintahkan untuk membunuh Mendez. Tapi, rencana ini justru membuat gerakan rakyat (grassroot) semakin besar. Dan pada 22 Desember 1988, Chico Mendez dibunuh di sebuah tempat yang tidak jauh dari rumahnya.
Tapi, benarlah pepatah jikalau gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, maka ia tinggal satu biji saja. Jika mati, maka ia akan tumbuh dan berbuah banyak...Kematian Chico Mendez tidak memadamkan api semangat para pejuang lingkungan. Sebaliknya, api itu semakin berkobar dengan munculnya gerakan-gerakan pelestarian lingkungan hidup.
read more...
















