 Pria berpostur gemuk dengan luka bakar di sekujur tubuhnya itu tampak gelisah. Sesekali, ia menatap kalender yang digantung di dinding ruangan berukuran 2X4 meter. Tanggal 14 Mei 2003. Matahari siang masih menghujamkan panasnya di Tanah Tinggi, Kawasan Senen. Patung panglima Tiongkok Kwang Kong dan seekor burung robin dalam sangkar seolah turut merasakan kegelisahan pria itu. Sejenak mereka hening. Iwan Firman (43), seorang korban Kerusuhan Mei 1998, takkan melupakan tanggal itu. Lima tahun lalu, pada tanggal yang sama, Iwan mengalami kekerasan yang membuat fisiknya cacat, tak senormal dulu. Siang itu juga, Iwan berbagi kisah tentang peristiwa horor Mei kelabu.
Pria berpostur gemuk dengan luka bakar di sekujur tubuhnya itu tampak gelisah. Sesekali, ia menatap kalender yang digantung di dinding ruangan berukuran 2X4 meter. Tanggal 14 Mei 2003. Matahari siang masih menghujamkan panasnya di Tanah Tinggi, Kawasan Senen. Patung panglima Tiongkok Kwang Kong dan seekor burung robin dalam sangkar seolah turut merasakan kegelisahan pria itu. Sejenak mereka hening. Iwan Firman (43), seorang korban Kerusuhan Mei 1998, takkan melupakan tanggal itu. Lima tahun lalu, pada tanggal yang sama, Iwan mengalami kekerasan yang membuat fisiknya cacat, tak senormal dulu. Siang itu juga, Iwan berbagi kisah tentang peristiwa horor Mei kelabu.
Kamis, 14 Mei 1998 pukul 8 pagi, Iwan ditelpon bosnya untuk melakukan tagihan ke Bekasi. Iwan yang adalah karyawan sebuah toko elektronik di Glodok ini segera menaiki Yamaha King Cobranya. Pagi itu, jalan-jalan masih normal. Ia menuju rumah bosnya di Pluit dan langsung meluncur ke Bekasi. Dari Bekasi, hari sudah siang. Iwan kembali ke Jakarta. Iwan heran memandangi jalanan. Mobil-mobil sudah terbalik dan terbakar. Api menyala melalap ruko-ruko di pinggiran jalan, menimbulkan asap tebal. Iwan merinding ketakutan. Ia mencari-cari orang untuk ditanyai apa yang terjadi. Tapi, ia tak menemui seorang pun. Sepi, katanya. Dari Bekasi, lalu Pondok Kranji, Cakung, Pulo Gadung, Perintis Kemerdekaan, Perempatan Coca-Cola, tampak suasana yang sama lagi mencekam. Siang menjelang sore, ia kembali Pluit menemui bosnya. Karena suasana sedemikian genting, bosnya menyuruh Iwan cepat-cepat pulang.
Kembali Yamaha king Cobra segera meluncur membawa sosok Iwan pulang. Pukul empat sore, di depan STM Poncol Cempaka Putih, terpaksa ia menghentikan motornya. Ia melihat ada segerombolan orang menghadang di jalan. Rambutnya cepak, mirip tentara, bercelanakan jeans plus pakaian preman. Mendapat isyarat buruk, segera ia membanting stir motornya ke belakang. Tak disangka, di belakang dia, sekelompok lain menghadangnya. Karena takut, ia buru-buru turun dari motornya dan berusaha kabur. Ia lari sekuat tenaga. Saat menoleh ke belakang, ia melihat 10 orang mengejar dia. Sayangnya, seorang dari kesepuluh orang itu berhasil menarik baju Iwan. Ia ketangkap. Iwan dipukuli beramai-ramai. Iwan mencoba melawan. Tapi, sia-sia saja. Mereka mencoba menyeret tubuh Iwan mendekati motornya yang ia parkir sekitar 20 meter dari tempat ia dipukuli. "Mau diapakan lagi diriku," batin Iwan. Ternyata, mereka membuka saluran bensin dari motornya yang berisi bensin penuh dan menguyurkannya ke tubuh Iwan. Lalu, seorang menyalakan korek api dan melemparkannya ke tubuh Iwan. Kontan, api langsung menyala membakar tubuh Iwan. Iwan pingsan.
Saat siuman, Iwan sadar bahwa dirinya sudah ada di ruang ICU Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sakit seolah menggerayangi tubuhnya. Daging tangan kanannya gosong dan mengelupas, kelihatan tulangnya. Sementara, tangan kirinya tak bisa digerakkan karena patah. Dan, Ibu jarinya sudah hilang terpanggang api. Di masa siuman itulah, Iwan menyadari bahwa dirinya selamat dari maut berkat pertolongan Pak Haji Harun, seorang haji tua asal gang Kranjang, Poncol dan sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu.
"Dokter, kalau begini caranya, untuk apa saya hidup," tutur Iwan mengenang saat ia tergolek di ranjang rumah sakit. Iwan mengaku tambah teriris hatinya karena istrinya tercinta tidak menengoknya. Padahal, satpam rumah sakit sudah ditugasi untuk mengabari istrinya soal kondisi Iwan. Namun, Iwan merasa diteguhkan saat teman-teman SMP-nya dulu datang rutin menengok. Bahkan, akunya, merekalah yang membiayai seluruh pengobatan yang mencapai 200 juta rupiah itu.
Empat bulan, Iwan dirawat di rumah sakit. Dengan kondisi belum sembuh benar, ia beranjak untuk mengunjungi istri dan kedua anaknya, Dewi Mustika (14) dan Yosua Santosa (12). Ia menuju Jl. Kembang Sepatu. Tak disangka, pertemuan hari itu menjadikan hati Iwan tambah sakit. Rupanya, istrinya tidak mau menerima lagi. "Kamu tidak perlu ke mari lagi. Kita sudah masing-masing saja," kata istrinya seperti yang ditirukan Iwan. Pupus harapan Iwan. Ia dicaci maki oleh istrinya. Ia diceraikan istrinya. Akhirnya, ia meninggalkan Jl. Kembang Sepatu menuju Tanah Tinggi, ke rumah kelahirannya.
Bila Sahabat Datang
Selain membuat tubuhnya cacat, peristiwa tragis itu membuat Iwan kehilangan pekerjaannya. Terpaksa, ia mengetuk dari pintu ke pintu untuk mengemis. Kadang ke Kota, kadang ke Jatinegara. Rahmat tersendiri bagi Iwan saat ia bertemu dengan sosok Andreas. Andreas adalah seorang penjual siomay yang sudah 33 tahun keliling menjajakan siomaynya di sekitar Tanah Tinggi. Tiap sore, ia lewat di depan rumah Iwan. Andreas, bapak yang enam bulan lalu ditinggal mati istrinya karena keropos tulang, menyediakan diri sebagai teman setia Iwan. Dialah yang menyediakan makan, memandikan, menceboki dan membantu Iwan melakukan aktivitasnya. Andreas menjadi tempat curhat Iwan dikala susah.
Hadir Andreas, hadir pula Abdillah. Penjaga palang kereta api Pos Pintu no. 31, Kembang Pacar, Pasar Gaplok, Senen ini mengaku telah menjalin persahabatan selama 20 tahun dengan Iwan. Bapak tua asal Brebes dan lebih dikenal sebagai Pak Kamat ini mengaku telah menyelamatkan Iwan dari niatnya bunuh diri di bantalan rel kereta api. "Jangan lakukan itu, Tuhanlah yang memberi keselamatan," kata Abdillah mengingat pengalaman itu. "Iwan itu temen akrab. Meskipun dia Cina, saya Jawa, kami sudah merasa seperti saudara. Iwan dulu suka menolong saya, kini giliran saya yang menolong Iwan," tutur Abdillah lalu beranjak memejet tombol merah, tanda kereta api datang. [Di dinding Pos Pintu itu, kami menemukan foto Iwan bersama seorang kawannnya sengaja ditempel oleh Abdillah].
tanda kereta api datang. [Di dinding Pos Pintu itu, kami menemukan foto Iwan bersama seorang kawannnya sengaja ditempel oleh Abdillah].
Dibantu sahabatnya tadi, Iwan kini mampu meneruskan usaha turun-temurun dari kakeknya, sebagai pedagang obat dan jamu Cina Sin She. Konon kabarnya, kakeknya menjadi saudagar jamu Sin She di Toko Tjap Singa Mas yang berdiri di kawasan segitiga Senen, kini telah menjadi Plaza Atrium. Setiap sore, ia menjaga kotak kaca berisi obat-obat Cina, menunggu pelanggan. Ia mengaku punya bakat menyembuhkan. Taka heran, beberapa pasien yang pernah ia tangani, seperti penderita kanker payudara, stroke, batuk darah, mengalami kesembuhan total.
Iwan terus menjalani hiduonya. Jalan masih panjang. Dengan sisa-sisa usia, energi, kecacatan tubuhnya, Iwan mencoba merajut beragam mimpi. Siang malam, ia terus bermimpi. Mimpi berkumpul kembali bersama istri dan kedua anaknya, mimpi agar orang-orang yang mencelakakan dirinya diadili, mimpi mendapat keadilan bersama korban-korban kekerasan negara lainnya. Mimpi seorang korban. Iwan namanya.
@published on Warta Minggu Juny, 1 2003
read more...
Sunday, February 19, 2006
Merajut Seribu Mimpi
Wednesday, February 08, 2006
Belajar Globalisasi
 Belajar tidak harus di kampus. Tidak juga di sekolah. Apalagi kalau sekolah hanya untuk transfer ilmu dari guru atau pun dosen. Lebih-lebih, untuk sekolah saja, biaya sangat mahal. Itu saja belum dengan kurikulum yang memasung dan memberatkan. Nah, bukannya membuat siswa cerdas, tapi justru bodoh dan tidak kritis. Ekstremnya, mendingan sekolah ditutup. Ivan Illich malah menegaskan bahwa sekolah sudah mati, school is dead.
Belajar tidak harus di kampus. Tidak juga di sekolah. Apalagi kalau sekolah hanya untuk transfer ilmu dari guru atau pun dosen. Lebih-lebih, untuk sekolah saja, biaya sangat mahal. Itu saja belum dengan kurikulum yang memasung dan memberatkan. Nah, bukannya membuat siswa cerdas, tapi justru bodoh dan tidak kritis. Ekstremnya, mendingan sekolah ditutup. Ivan Illich malah menegaskan bahwa sekolah sudah mati, school is dead.
Kami tidak seekstrem Ivan Illich. Yang jelas, kami haus belajar. Dan kesempatan belajar itu tidak kami cari, tetapi kami ciptakan. Lahirlah komunitas studi bernama Rural Community (selanjutnya disingkat RC). Nama RC adalah buah usulan dari Mariana Ari, salah satu anggota komunitas. Kelahiran komunitas ini berkat perkawinan ide-ide kami bersepuluh, yakni Budi Pruwanto, Mariana Ari, Anna, Daniel Awigra, Sakura, Felix IW, Fr. Benny SJ, Nara Patrianila, Olive, dan aku sendiri.
Fokus kajian RC adalah neoliberalisme atau globalisasi. Mengapa kami mempelajari Neoliberalisme? Neoliberalisme semakin nampak sebagai bentuk penjajahan global. Globalisasi yang selama ini digaungkan sebagai proses pembudayaan, pengantasan kemiskinan, penghapus kelaparan, ternyata menjadi fenomena penindasan budaya global, pencetak kelaparan dan kemiskinan global, dan perampasan global. Inilah penjajahan ekonomi. Aktornya adalah korporasi-korporasi multinasional yang bersekutu dengan negara adikuasa dan lembaga-lembaga keuangan dunia, seperti IMF, WTO, dan WB. John Perkins dalam Confessions of an Economic Hit Man menyebutnya sebagai corporatocracy.
Teriakan anti globalisasi bergema di mana-mana. Desember tahun lalu, puluhan ribu pengunjuk rasa antiglobalisasi tumpah di jalan-jalan Kota Hongkong tempat diadakannya sidang WTO. Yel-yel festival jalanan itu menghentak dan menggetarkan langit-langit kota Hongkong.
Nah, kami mau mempelajari fenomena aktual dan dekat dengan hidup keseharian itu, globalisasi. Kami mencoba mempelajarinya dari asal muasalnya, terminologinya, mekanismenya, pemain-pemain utamanya, dampak-dampaknya (budaya, ekonomi, sosial, politik), resistensi-resistensinya, dan sebagainya. Fenomena ini, bagi kami, layak dipelajari karena ini sama saja mempelajari hidup itu sendiri. Giddens sendiri menegaskan, globalisasi bukan sekadar perkara yang ada di luar sana, tetapi juga yang ada di sini. Misalnya, menyangkut identitas diri.
Pada Minggu, 26 Januari 2006, ketika banyak orang sedang mengisi liburan dan berburu ampao di hari Imlek, kelas pertama dimulai. Di sekretariat RC, Jl. Ubud, Mega Kuningan, Jakarta, aku membawakan paperku. Aku mengantar diskusi Studium Generale, studi umum, tentang Neoliberalisme. Paper ini aku beri judul “Ziarah dari Global Village Menuju Global Pillage.” Dari kampung global, menuju penjarahan global. [Artikel keseluruhan bisa dibaca dengan mengklik: Studium Generale]
Paling tidak, komunitas ini senantiasa memacuku untuk on going study. Belajar tak pernah berhenti. Bergumul dengan buku-buku tebal dan artikel-artikel berat, sambil senantiasa menajamkan daya-daya jiwa seperti indra, budi, hati, untuk memandang dunia, menjadi sebuah irama yang menarik dalam hidup studi.
Aku selalu memegang kata-kata James Nacthwey, fotografer perang, yang mengatakan, “Aku tidak menganggap diriku tahu segalanya, tetapi aku belajar dari segalanya.” Toh, belajar pasti bermanfaat, untukku, untukmu, dan untuk dunia....
 Dari kiri ke kanan: Mariana Ari, Anna, dan Budi Pruwanto, sedang serius tapi santai dalam belajar globalisasi. [fotografer: Awigra]
Dari kiri ke kanan: Mariana Ari, Anna, dan Budi Pruwanto, sedang serius tapi santai dalam belajar globalisasi. [fotografer: Awigra]
[You can read this english version by clicking English Edition]
read more...Tuesday, February 07, 2006
Membohongi Pak Polisi
 Razia polisi digelar malam itu, Senin (6/2) di pertigaan Jl. Kemanggisan Raya, dekat warung ayam bakar Bu Cecep. Ini sudah kesekian kalinya, razia sepeda motor digelar. Tapi, kesekian kali ini pula, aku lepas begitu saja dari para aparat itu. Ketika seorang polisi tua mencegatku, aku menghentikan sejenak motorku. Sebelum dia sempat ngomong, aku sudah ngomong duluan, “Pak lagi deadline majalah. Saya harus cepat-cepat ke kantor karena sudah mau cetak.” Dengan sedikit terbengong, polisi itu bertanya, “Dari media mana?” Jawabku, “Leadershippark!”. Tanpa pikir panjang, polisi itu segera mempersilakan aku lewat. Aku tertawa dalam hati, ha ha ha, dan selamat tiba di rumah.
Razia polisi digelar malam itu, Senin (6/2) di pertigaan Jl. Kemanggisan Raya, dekat warung ayam bakar Bu Cecep. Ini sudah kesekian kalinya, razia sepeda motor digelar. Tapi, kesekian kali ini pula, aku lepas begitu saja dari para aparat itu. Ketika seorang polisi tua mencegatku, aku menghentikan sejenak motorku. Sebelum dia sempat ngomong, aku sudah ngomong duluan, “Pak lagi deadline majalah. Saya harus cepat-cepat ke kantor karena sudah mau cetak.” Dengan sedikit terbengong, polisi itu bertanya, “Dari media mana?” Jawabku, “Leadershippark!”. Tanpa pikir panjang, polisi itu segera mempersilakan aku lewat. Aku tertawa dalam hati, ha ha ha, dan selamat tiba di rumah.
Membohongi polisi bukan pengalaman sekali. Tapi berkali-kali. Dulu, aku bersama Edi, fotografer Majalah Pengusaha, melintas Jalan Pemuda di suatu siang. Di depan, tampak satuan polisi merazia sepeda motor yang lewat. Edi sendiri tidak pakai helm. Motorku semakin dekat dengan arena razia. Belum sempat motorku berhenti dan polisi ngomong aku teriak, "Pak mau liputan kriminal!” Jawab polisi muda itu, “O, ya. Sana cepat liputan kriminal!”
Aku dan Edi tak bisa menahan ketawa. Batinku, “Baru kali ini, aku disuruh cepat-cepat oleh polisi untuk liputan kriminal. Siapa kalau begini yang seharusnya disebut kriminal?”
Kejadian serupa menimpaku di bawah jalan layang Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pagi itu, aku membelokkan motorku lewat bawah, memutar melawan arus samping Gedung BCA. Sebenarnya, aku memang salah karena ini verboden. Eh, ada razia tepat di bawah jalan layang. Aku distop pak polisi dan sebelum dia ngomong, saya menyahut, “Pak, mau liputan kriminal di Polres Jakarta Barat situ.” Aku segera mengacungkan telunjukku ke arah kantor polres Jakarta Barat di Jl. S. Parman yang tak jauh dari tempat razia. Polisi itu lalu mengayunkan tangannya dan mempersilakan aku lewat. Hi hi hi….berbohong lagi neh…
Frase “liputan kriminal” inilah menjadi kata sakti bagiku menghadapi razia. Dan aku ngomong duluan sebelum pak polisi angkat bicara adalah modus operandinya. Sebenarnya, kalau diperiksa kartu-kartu identitasku lengkap, entah SIM, STNK, Kartu Pers. Tapi, kartu SIM-ku sudah mati alias expired dan males aku perpanjang. Padahal sudah dua tahun lebih.
“Pak polisi, tangkaplah aku!” aku sudah jujur neh….dasar wartawan.
read more...
Monday, February 06, 2006
Pramoedya in The Blank Cassette
 Kecewa. Cukup sedih. Itulah kata yang tepat menggambarkan suasana hatiku setelah kaset untuk merekam orasi Pramoedya Ananta Toer ternyata blank. Kosong. Tanpa kata-kata Pramoedya yang keluar dalam suaranya yang tegas-tegas parau. Hanya suara ‘kemresek’ (berisik ala bunyi hujan) yang ada. “Dasar tape keparat!” umpatku malam ini, malam setelah menghadiri perayaan Ulang Tahun Maestro Sastra itu yang ke-81, di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Senin (6/2).
Kecewa. Cukup sedih. Itulah kata yang tepat menggambarkan suasana hatiku setelah kaset untuk merekam orasi Pramoedya Ananta Toer ternyata blank. Kosong. Tanpa kata-kata Pramoedya yang keluar dalam suaranya yang tegas-tegas parau. Hanya suara ‘kemresek’ (berisik ala bunyi hujan) yang ada. “Dasar tape keparat!” umpatku malam ini, malam setelah menghadiri perayaan Ulang Tahun Maestro Sastra itu yang ke-81, di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Senin (6/2).
Padahal aku sempat berbangga dan optimis bakalan membuat feature tentang sepenggal kisah Pramoedya dengan bagus.  Di malam itu, aku juga sempat merekam komentar beberapa orang tentang sastrawan yang baru saja menerbitkan novel terbarunya, Jalan Raya Pos, Jalan Daendels (2005). Misalnya, Andreas Harsono, orang yang baru saja mengomentari weblogku ini. Dialah jurnalis senior yang sudah melalang buana dan menjadi guru jurnalistik. Dia pernah berguru pada Robert Vare, mantan editor The New Yorker dan juga Bill Kovach, jurnalis kondang dan kurator Newman Foundation. Aku semakin mengenal dan diam-diam belajar jurnalistik darinya lewat blognya, http://www.andreasharsono.blogspot.com Aku mengutarakan harapanku di web blog bisa bertemu dengannya. Eh, tak lama dan tak disangka, ketemu juga di Teater Kecil.
Di malam itu, aku juga sempat merekam komentar beberapa orang tentang sastrawan yang baru saja menerbitkan novel terbarunya, Jalan Raya Pos, Jalan Daendels (2005). Misalnya, Andreas Harsono, orang yang baru saja mengomentari weblogku ini. Dialah jurnalis senior yang sudah melalang buana dan menjadi guru jurnalistik. Dia pernah berguru pada Robert Vare, mantan editor The New Yorker dan juga Bill Kovach, jurnalis kondang dan kurator Newman Foundation. Aku semakin mengenal dan diam-diam belajar jurnalistik darinya lewat blognya, http://www.andreasharsono.blogspot.com Aku mengutarakan harapanku di web blog bisa bertemu dengannya. Eh, tak lama dan tak disangka, ketemu juga di Teater Kecil.
Aku juga sempat mewawancarai Muhidin M. Dahlan yang mengarang novel “Tuhan Izinkan Aku jadi Pelacur.” Sejauh aku ingat, dia mengaku dua hari lalu bertemu dengan Pramoedya. Dia mengaku mengagumi Pramoedya soal keberanian dan ketekunannya. Pramoedya tekun membuat kliping.
Tak kalah menarik, aku juga sempat mewawancarai Max Lane. Max Lane menjadi penerjemah pertama Tetralogi Pramoedya (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca) dalam bahasa Inggris. Bersama istrinya, Faiza Mardzoeki, Max tinggal di Australia dan mengajar tentang Indonesia di Sidney University. Faiza sendiri sedang memproduseri teater yang mengambil salah satu tokoh dalam novel Pram, yakni Nyi Ontosoroh. Rencananya, teater ini akan pentas Agustus mendatang. Untung saja, aku mendapatkan nomer kontak Faiza dan alamat email Max Lane. Segera, malam ini juga, aku menyusun pertanyaan dan akan aku kirimkan ke Max Lane lewat email. Waduh, sayang sekali. Inilah namanya sial. Tapi, aku bisa merekam sepenggal jejak Pram dengan kameraku, plus memoriku.
penerjemah pertama Tetralogi Pramoedya (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca) dalam bahasa Inggris. Bersama istrinya, Faiza Mardzoeki, Max tinggal di Australia dan mengajar tentang Indonesia di Sidney University. Faiza sendiri sedang memproduseri teater yang mengambil salah satu tokoh dalam novel Pram, yakni Nyi Ontosoroh. Rencananya, teater ini akan pentas Agustus mendatang. Untung saja, aku mendapatkan nomer kontak Faiza dan alamat email Max Lane. Segera, malam ini juga, aku menyusun pertanyaan dan akan aku kirimkan ke Max Lane lewat email. Waduh, sayang sekali. Inilah namanya sial. Tapi, aku bisa merekam sepenggal jejak Pram dengan kameraku, plus memoriku.
Pramoedya, dalam ingatanku, tetap tampil seperti sebelumnya. Masih sama seperti ketika berorasi di HUT-nya yang ke-80 tahun lalu. Ia tampil sederhana, penuh senyum. Meski beberapa saat lalu, Pram dikabarkan sakit. Dibalut dengan kemeja putih lengan panjang dan celana training warna coklat susu bergaris putih, Pram masuk ke Teater Kecil. Dengan langkah pelan dan ditemani tongkatnya, Pram melihat-lihat dulu poster-poster bukunya yang di pamerkan.
Ditemani oleh budayawan Taufik Razen, Pram berdialog dengan para audiens yang kebanyakan adalah orang muda. Pram masih lantang. Khususnya, bila berkomentar tentang orang muda. Meskipun, ia senantiasa dibisiki Taufik lantaran pendengarannya sudah kurang. Ia mengulang yang pernah ia sampaikan, bahwa orang muda adalah pembuat sejarah Indonesia. Tapi, ia menyayangkan tidak diperhatikannya sejarah Sumpah Pemuda oleh orang muda. Lebih-lebih, orang muda belum mampu melahirkan seorang pemimpin. Pemimpin seperti apa? Jawabnya tegas, Soekarno. Ini juga dikarenakan tidak dibangunnya sebuah karakter.
Sastrawan kelahiran Blora, 6 Februari 1925 ini mengajak orang muda untuk produktif. Katanya, bangsa ini lebih banyak konsumsinya ketimbang produktifnya. Lebarnya jurang antara konsumsi dan produksi itu telah melahirkan ‘benu a’ yang namanya korupsi.
a’ yang namanya korupsi.
Dialog cukup menarik. Seorang muda menanyakan soal rencana seorang produser memfilmkan novel Bumi Manusia. Pram menjawab bahwa Bumi Manusia boleh difilmkan asal diganti dengan uang Rp 1,5 miliar. Sontak, jawaban Pram memicu reaksi beragam. Aktivis Yeni Rosa Damayanti, berteriak kecewa. Pram dinilainya seperti seorang kapitalis. Yeni protes kenapa karya-karya Pram dinilai dengan uang dan kawatir kalau ada anak-anak Negeri yang ingin mengekspresikan karya-karyanya tidak mampu lantaran tidak punya uang. Pram sendiri menjawab itu sudah menjadi hak cipta dari karya-karyanya. Ia bebas memperlakukan karya-karyanya itu. Dan ia prihatin banyak orang yang tidak peduli dengan karya-karyanya sejak tahun 1965 sampai kejatuhan Soeharto. 
Yang lain menimpali dengan ketidaksetujuan dengan Yeni. Katanya, Pram berhak dengan karya-karyanya. Patokan harga tinggi itu layak buat karya besar seperti karya Pram. Ini tidak lepas dari konteks historis Pramoedya sendiri. Toh, katanya, penulis di negeri ini kurang dihargai. Max Lane juga tidak setuju Pram dikatakan bergaya kapitalis. Yang kapitalis justru para produsen film, pengarang tidak. Sementara, Faiza Mardzoeki mengatakan bahwa ia sudah dapat izin gratis untuk menampilkan karya Pram dalam teater dengan tokoh Nyi Ontosoroh. Kata Faiza, ini bukti Pram bahwa Pram cukup membedakan mana yang untuk rakyat dan mana yang bukan. Seorang lagi menambahi bahwa karya Pram pernah diminta produser luar negeri untuk difilmkan. Pram menolak keras. Pasalnya, Pram ingin karyanya difilmkan oleh anak-anak Indonesia sendiri.
HUT mantan penghuni b ui Pulau Buru itu juga dimeriahkan dengan pentas seni dari orang muda. Antara lain, Rieke Diah Pitaloka dengan pembacaan puisinya, pentas musik grup Local Ambience, Adit (cucu Pram) grup, dan grup Marginal. Grup Marginal, grup anak muda Punk, tampil meriah karena suporternya tumpah di depan panggung ikut berjoget. Bahkan, grup ini memberi gelar Pramoedya sebagai Datuk Punk, selain julukan Sastrawan 32 batang rokok.
ui Pulau Buru itu juga dimeriahkan dengan pentas seni dari orang muda. Antara lain, Rieke Diah Pitaloka dengan pembacaan puisinya, pentas musik grup Local Ambience, Adit (cucu Pram) grup, dan grup Marginal. Grup Marginal, grup anak muda Punk, tampil meriah karena suporternya tumpah di depan panggung ikut berjoget. Bahkan, grup ini memberi gelar Pramoedya sebagai Datuk Punk, selain julukan Sastrawan 32 batang rokok.
Itulah sekilas laporan pandangan mata tentang Pramoedya. Bagiku, malam itu adalah malam inspirasi. Eksistensi Pramoedya adalah menulis. Apalagi, Sang Maestro pernah berpesan, "Tahukah kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapa pun? Karena kau menulis. Suaramu takkan padam ditelan angin, akan abadi, sampai jauh, jauh di kemudian hari..."
[You can read this english version by clicking: english edition]
read more...
Sunday, February 05, 2006
Apakah Aku Ikut Membunuhnya?

Pojok jalan Sang Timur, depan gedung paroki dan dekat warung nasi padang, kini lengang. Sosok lelaki, umur 35 tahunan, tidak pernah nongkrong lagi di pojok jalan itu. Sudah dua bulan, saat sosok itu raib abadi alias mati. Maskun, nama lelaki itu. Ia mati karena ginjalnya aus, tak berfungsi lagi. Namun, bayangan Maskun tak juga hengkang dari ingatanku. Bahkan, berkali-kali bayangan itu muncul dengan jelas. Berkali-kali pula, ia menyapaku, “Mas Sigit, mampir!” Membangkitkan rasa bersalahku. Aku pun tak kuasa menyembunyikan ketakutanku.
Rasanya, ingin selamanya kuhindari pojok jalan itu. Memang, pojok jalan itu sering aku lalui kalau aku mau ke redaksi majalah paroki,. Di pojok itu, hampir setiap saat, Maskun nongkrong bersama tukang tempe goreng, dan selalu menyapaku. “Mas Sigit, mampir!” katanya saat aku melaju dengan Honda Supra-X ku.
Aku kenal Maskun sudah lama, meski tidak intensif. Aku kenal dia saat ada pelatihan fasilitator di Forum Kemanusiaan (FK), sebuah komunitas orangmuda yang peduli pada pendidikan anak-anak miskin. Kantor FK berderet dengan rumah Maskun. Tak jauh dari gedung gereja. Sehari-hari, ia menunggui rental play station yang tak sepi diserbu anak-anak dari kampung Satelit. Kampung Satelit terpisah tembok 15 cm dengan kompleks gereja. Namun, keduanya tampak sebagai dua realitas yang kontras. Satelit sarat dengan rumah-rumah padat, bangunan reot, tampak kumuh, dan berwajah miskin. Gedung paroki tampil mentereng dengan pembangunan gedung yang mewah dan berwajah kaya.
Sapaan Maskun sering kuanggap sepi. Toh, bila aku tanggapi sebatas lambaian tangan, sapaan singkat, maupun bunyi klakson motorku. Tapi, jarang sekali aku menyempatkan diri untuk mampir. Namun, pojok jalan ini tidak sebatas kenangan. Ia selalu menggelisahkanku. Membuatku sedikit gemetar. “Apakah aku ikut membunuhnya?” Pertanyaan aneh, tapi ada sejarahnya.
Sebulan sebelum maut menjemputnya, aku dapat kabar dari Enim, temen FK, bahwa Maskun sakit dan dirawat di Rumah Sakit. Enim, gadis berjilbab, menghampiriku suatu hari. Kata Enim, Maskun terancam pulang dari rumah sakit karena kekurangan biaya. Padahal, sakitnya lumayan parah. Aku turut bersimpati. Enim memintaku menolong Maskun. Aktivis perempuan itu memintaku untuk menulis di majalah paroki perihal sakitnya Maskun. Aku menyanggupinya karena di majalah paroki ada rubrik peduli kasih. Rubrik ini khusus diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan bantuan dana dan dukungan moral. Aku pun sering ditugasi mengisi rubrik ini.
Aku bersyukur, dengan menulis di rubrik ini ternyata aku bisa membantu banyak orang. Tulisan yang berdaya guna. Dulu, berkat feature yang kutulis, Rendie, bocah kecil asal Kepa Duri mampu berobat sampai sembuh di RS Graha Medika. Rendie mengalami luka infeksi di bagian perut akibat diserempet bus. Lukanya membusuk, sampai dihiasi belatung. Kemiskinan memaksa keluarga Rendie angkat tangan mengobatinya secara layak. Ayahnya berprofesi sebagai tukang listrik sekolah dan mamanya mengalami gangguan mental. Tapi, feature itu mampu memanggil banyak orang untuk membantu penyembuhan Rendie. Rendie akhirnya bisa sekolah lagi.
Ada Rendie, ada juga Iwan. Iwan adalah salah seorang korban kerusuhan Mei 1998. Tubuhnya cacat akibat dibakar dengan bensin di Cempaka Putih. Sosoknya, aku wawancara persis di lima tahun sejak kerusuhan itu terjadi, 14 Mei 2003. Lagi, featureku mampu menggugah seorang ibu muda yang setelah membaca tulisan itu, ingin bertemu dengan Iwan dan menyerahkan sedekah.
Masih ada sosok
 Frederick, bayi laki-laki yang mempunyai kelainan jantung. Setelah membaca featureku, banyak donatur menyokong orangtua Frederick yang nota bene tidak mampu membiayai seluruh pengobatan. Frederick kini menjadi bocah sehat dan menggemaskan. Ada lagi, sosok Sin An, lelaki muda, yang kelainan ginjal dan berobat di Cina. Lagi-lagi, tulisan yang kubuat mampu mengetuk orang lain untuk membantu sesamanya. Dengan itu, aku bersyukur. Tenyata, aku pun bisa bersolider dengan orang lain dengan tulisan. Karenanya, aku senang bila mengisi rubrik feature ini.
Frederick, bayi laki-laki yang mempunyai kelainan jantung. Setelah membaca featureku, banyak donatur menyokong orangtua Frederick yang nota bene tidak mampu membiayai seluruh pengobatan. Frederick kini menjadi bocah sehat dan menggemaskan. Ada lagi, sosok Sin An, lelaki muda, yang kelainan ginjal dan berobat di Cina. Lagi-lagi, tulisan yang kubuat mampu mengetuk orang lain untuk membantu sesamanya. Dengan itu, aku bersyukur. Tenyata, aku pun bisa bersolider dengan orang lain dengan tulisan. Karenanya, aku senang bila mengisi rubrik feature ini.Namun, lain cerita dengan Maskun. Semula, aku semangat menjanjikan menulis featurenya. Bahkan, sempat aku menghubungi redpelku, meski tanggapannya kurang jelas. Tapi, masa-masa itu adalah masa di mana aku lagi bosan-bosannya berurusan dengan Gereja. Males dan tak mau peduli. Gereja sungguh berwarna negatif di mataku. Lelah juga rasanya beraktivitas di dalam Gereja. Bahkan, tulisan-tulisanku yang bernada kritik malah membuat semakin banyak orang terasa mencibirku. Aku merasa kesepiaan dan rasanya jadi orang asing di negeri sendiri. Namun, mungkin ini hanya perasaanku saja. Kejengkelanku semakin menjadi dengan keputusanku tidak mau berelasi dengan paroki lagi. Termasuk tidak mau berurusan dengan media paroki lagi. Aku mau jeda. Ini terjadi sampai beberapa minggu...
Sampai akhirnya...
Di suatu malam, pukul 23.50, ponselku tiba-tiba berbunyi. Memecah keheningan dan kenyamanan diriku yang nyaris lelap. “Halo, ini mas Sigit ya, temennya Maskun di FK. Ini saya, adiknya Maskun. Cuma mau mengabarkan, Maskun baru saja meninggal. Minta tolong untuk meneruskan kabar ini ke teman-teman FK lainnya ya. Terimakasih,” demikian suara perempuan berbicara di ponselku.
Sontak aku kaget. Rasanya tidak percaya. Kesedihan dan kekecewaan dengan cepatnya menyapu keheningan dan kenyamanan malam itu. Aku baru saja ingat akan janjiku. Janji untuk menulis feature di rubrik peduli kasih tentang sakitnya Maskun. Aku lupa! Benar-benar lupa. Dan kini sudah terlambat untuk menuliskannya. Aku marah besar dengan diriku sendiri. Aku gelisah. Tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sepintas pertanyaan menakutkan itu menggelayut dalam hati, “Aku turut andil dalam kematiannya?”
Aku mencoba tenang. Untuk memastikan, aku telpon balik via ponsel yang sedang aku charge.
“Mbak, ini aku temennya Maskun yang tadi. Sekarang, Maskun di mana?” tanyaku.
“Sudah lama, di rumah. Ia meninggal di rumah,” katanya dengan nada sendu.
“Saya lihat di buku telponnya Maskun. Dan di situ, tertulis nomernya Mas Sigit. Saya belum menghubungi temen yang lain. Tolong ya Mas, tolong sampaikan pada teman-teman yang lain...” katanya lagi.
Jawaban ini kembali menusuk hatiku. Aku rasa, akulah kawan pertama yang diberi kabar soal kematian Maskun. Kenapa, perempuan itu memilih nomer ku di buku telponnya Maskun? Kenapa tidak pada nomer-nomer yang lain. Aku merasa Maskun sendirilah yang memilihkan nomer itu. Seolah-olah, Maskun mau menagih janjiku. Sapaan-sapaan di pojok jalan itu, seakan kembali terdengar. Aku jadi gemetar, sedih campur rasa bersalah. Aku tidak bisa tidur.
Aku mulai bermonolog. Kesalahan terbesarku, yakni aku lupa menulis feature buat Maskun. Padahal, aku sudah menyanggupi. Namun, kejengkelannku dengan paroki membuatku lupa semuanya. Lupa pada Maskun, sampai akhirnya sudah terlambat. Maskun sudah terlanjur pergi, tak kuasa melawan sakitnya. Andaikan aku menulis featurenya. Mungkin saja, banyak orang terketuk untuk memberi donor, dan meringankan biaya perawatannya. Maskun tidak perlu mundur dari rumah sakit. Ia pasti akan dirawat dan kemungkinan juga bisa sembuh. Ia akan sembuh, tetap hidup, dan terus menyapaku di pojok jalan saat aku lewat.
Tapi, realitas bicara lain. Maskun mundur dari rumah sakit karena tidak punya biaya. Di rumah, ia menggumuli sakitnya, sampai kematian menghampirinya. Mungkin pula, realitas akan berjalan lain kalau aku tidak lupa menuliskannya. Bukannya aku sombong, tapi perasaan bersalah sempat menjadi momok hatiku. Aku turut membunuhnya? Penyakit itu sedang membunuhnya, dan aku mempercepat kematiannya?
Kalau pun itu kutulis sekarang, jelas tidak ada gunanya. Tulisanku juga tidak mampu membangkitkannya dari kubur. Tulisanku juga takkan mampu menghapus nama yang terpatri di batu nisannya. Semua sudah terlambat. Tinggal sejarah, sejarah penyesalan.
Akhirnya, aku aku angkat tangan. Aku bukan Tuhan. Biarlah kematian menjadi urusan Tuhan, sama seperti ketika kehidupan itu ada. Ada dan tidak ada bukan wewenangku. Aku hanya menyadari bahwa aku ada, dan berusaha memelihara dan mengembangkan ada itu, sampai waktunya ada itu tidak ada lagi.
Aku belajar banyak dari kematian Maskun. Yang jelas, kini aku sadar, menulis itu pekerjaan mulia. Menulis juga panggilan. Menulis bukan suatu yang main-main. Paling tidak, Maskun memberi pelajaran yang tidak bakalan kulupakan.
Sementara itu, pojok jalan itu tetap terlihat lengang. Sepi. Basah oleh hujan yang mengguyur sore tadi...
@ malam, saat terkenang Maskun
Thursday, February 02, 2006
The New Rulers of The World
 Menonton film garapan John Pilger, wartawan Australia, berjudul The New Rulers of The World membuat hati ini sedih. Pasalnya, dengan gamblang nampak betapa Bangsa Indonesia masih menjadi Bangsa yang terjajah. Dulu, Indonesia mengalami kolonialisme militer oleh Belanda ratusan tahun. Sekarang, di antara deru globalisasi, Indonesia dan bangsa-bangsa lain khususnya di Asia, dijajah secara ekonomi.
Menonton film garapan John Pilger, wartawan Australia, berjudul The New Rulers of The World membuat hati ini sedih. Pasalnya, dengan gamblang nampak betapa Bangsa Indonesia masih menjadi Bangsa yang terjajah. Dulu, Indonesia mengalami kolonialisme militer oleh Belanda ratusan tahun. Sekarang, di antara deru globalisasi, Indonesia dan bangsa-bangsa lain khususnya di Asia, dijajah secara ekonomi.
Negeri yang kaya potensi ini, menjadi negeri yang miskin dan pengemis. Demikianlah ungkap Maestro sastra Indonesia Pramoedya Ananta Toer dalam penggalan wawancara pada film itu. John Pilger mampu memotret bagaimana korporasi-korporasi multinasional (MNC) yang berinvestasi di Negeri ini melakukan praktek ketidakadilan dan eksploitasi pada para ribuan buruh, masyarakat, dan alam Indonesia.
Lembaga-lembaga donor dan keuangan dunia seperti World Trade Organization (WTO), International Monetery Fund (IMF), dan World Bank (WB) turut menjadi pemain-pemain utama dalam praktek itu. Mereka bagaikan dewa penyelamat menggelontorkan utang-utang kepada negara-negara miskin dan Dunia Ketiga. Tapi, bukan untuk membantu. Sebaliknya, negara-negara miskin ini semakin terpuruk dalam kemiskinan. Utang-utang itu menjadi sarana yang jitu bagi korporasi-korporasi multinasional untuk masuk dan berinvestasi ke negara-negara itu. Janji tinggalah sebagai janji. Terjadilah jurang yang semakin lebar antara yang kaya (the have) dan yang miskin (the have not). Lembaga-lembaga itulah yang menjadi para pengatur dunia yang baru.
Negara yang tugasnya mengayomi rakyat, berselingkuh dengan para korporasi global ini. Utang yang harusnya untuk rakyat, telah dimakan oleh pemerintahan yang korup. Sementara, negara dengan enaknya menjual rakyatnya sendiri.
Aku sangat appreciate dengan film ini. Dengan jelas, nampak bagaimana kiprah korporasi dan institusi keuangan global mampu mengguncang kehidupan sosial politik sebuah negara. Indonesia namanya.
John Pilger lahir di Sydney. Ia profesional menerapkan jurnalisme investigasi. Ia mendapat banyak penghargaan. Di antaranya, International Reporter of the Year (1970) dan United Nations Association Media Prize. Untuk televisi, ia memenangi American Television Academy Award (1991) dan Richard Dimbleby Award.
Ada kalimat menarik dari John Pilger yang menjadi ‘pencerahan’ buat para jurnalis. “It is not enough for journalist to see themselves as mere messengers without understanding the hidden agendas of the message and the myth that sorround it,” katanya.
(bdk. www. Johnpilger.com)
read more...
Wednesday, February 01, 2006
Menggali Harta Sang Alkemis
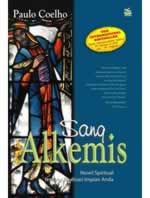 Judul : Sang Alkemis
Judul : Sang Alkemis
Pengarang : Paulo Coelho
Penerbit : Pustaka Alvabet, 2005
Cetakan : VII
Tebal : 193 hlm.
Karya klasik modern Paulo Coelho ini memang cukup memukau. Novel garapan penulis Brazil ini berkisah tentang suka duka peziarahan bocah kecil bernama Santiago, bocah gembala di Andalusia, mencari harta karun. Perjalanan dimulai dari Spanyol menuju Tangier. Perjalanan panjang memakan ribuan kilometer. Di rentetan jejak langkahnya, Santiago bertemu dengan beragam orang dan beragam pengalaman unik. Ia menyeberangi gurun Mesir. Di sebuah oasis, ia mengalami perjumpaan yang menentukan dengan seorang Alkemis. Di gurun, ia pun menemukan kekasih hatinya, Fatima. Perjumpaan-perjumpaan yang menjadi ruang pembelajaran secara spiritual soal pencapaian cita-cita hidup.
Kejutan pertama ketika Santiago berjumpa dengan orangtua bernama Melchizedek. Obrolan dibuka dengan topik buku yang ditenteng bocah itu. Dari buku itu, ada perhatian soal usaha mewujudkan Legenda Pribadi. Masing-masing orang punya Legenda Pribadi atau mimpi dan cita-citanya. Orangtua yang mengaku Raja Salem itu melihat banyaknya ketidakmampuan orang untuk memilih Legenda Pribadinya. Bahkan, banyak orang yang akhirnya menyerahkan hidupnya pada nasib. Orangtua itu juga menasihati, saat orang menginginkan sesuatu, alam semesta bersatu untuk membantu orang itu meraihnya.
Santiago terus berjuang menggapai mimpinya. Ia terus membaca tanda tanda kehidupan, seperti yang Melchizedek katakan, untuk cita-citanya itu. Sebelum berpisah, Melchizedek memberikan dua buah batu penolong membaca tanda. Keduanya diberi nama Urim dan Thummim. Raja tua berbaju lusuh itu hanya berpesan, “Jangan pernah berhenti bermimpi, ikutilah pertanda.”
Anak muda ini melanjutkan perjalanan ke Tangier, sebuah kota pelabuhan di Afrika. Di sana, ia bekerja di sebuah toko kristal. Perjumpaan dengan si empunya toko membuat Santiago semakin terbuka pada cita-citanya. Si empunya toko digambarkan sebagai orang merasa terlambat untuk mewujudkan Legenda Pribadinya. Ia takut pada perubahan. Ia lebih menikmati hidupnya di ruang tokonya selama 30 tahun. Konon, ia punya mimpi untuk pergi ke Mekah dengan menyusuri gurun, dan mengitari Kabah tujuh kali. Tapi, ia ragu dan takut gagal. Ia memutuskan tinggal memimpikannya saja.
Setelah bekal dirasa cukup, Santiago melanjutkan perjalanan. Ia bertemu dengan lelaki Inggris yang bertahun-tahun mencari Sang Alkemis, Batu Filsuf, dan Obat Hidup. Kata orang, Alkemis termasyur ada di Arab, di oasis Al-Fayoum. Pada momen ini, Santiago menemukan gadis gurun bernama Fatima. Ia jatuh cinta. Santiago memberanikan diri bilang cinta. Fatima berujar, “Seorang dicintai karena ia dicintai. Tak perlu ada alasan untuk mencintai.” Lagi-lagi, sebuah refleksi mendalam yang masuk dalam novel ini.
Pada fase padang gurun ini, dimana dilatari perang antar suku, Santiago berjumpa dengan penunggang kuda. Tak lain adalah Sang Alkemis. Sebuah perjumpaan yang sangat menentukan. Keduanya terlibat dalam dialog-dialog menarik yang menambah bobot pada novel ini. Novel ini mampu melibatkan pembaca untuk terlibat dalam dialog dan berrefleksi atas kehidupannya sendiri. Tak lain karena apa yang didialogkan dalam novel ini dekat sekali dengan kehidupan pembaca. Tentunya, pembaca seperti Santiago mempunyai mimpi dan cita-cita dalam hidupnya.
Sang Alkemis mengatakan, untuk memahami Jiwa Buana, jiwa meraih cita-cita, orang harus mempunyai keberanian. Mewujudkan impian memang tidak mudah, bahkan menakutkan. “Memang menakutkan dalam mengejar impianmu, kau mungkin kehilangan semua yang telah kau dapatkan,” kata Alkemis. Bagi Alkemis, hanya satu hal yang membuat mimpi tidak dapat diraih, yakni perasaan takut gagal. Santiago mendapat pelajaran berharga dari Sang Alkemis. Tapi, setelah mendapat bekal berharga itu, apakah Santiago berhasil menemukan harta karun dan mewujudkan mimpinya?
Novel ini memang layak dimasukan dalam genre novel spiritual tentang realisasi sebuah impian. Paulo Coelho berhasil dalam mengawinkan refleksi spiritual dengan sastra. Mengajak pembaca tidak hanya menikmati hiburan kisah saja, tetapi terlibat dalam narasi karena apa yang dibaca tak lain adalah cermin kehidupan. Kekuatan ini pula yang tampak dalam novelnya yang lain, ‘Veronika Memutuskan Mati’, ‘Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk Tersedu’ dan ‘O Zahir.’ Coelho pun dianggap sebagai satu dari lima pengarang terbesar sepanjang sejarah dan meraih beragam penghargaan.
[Pernah dimuat di Majalah LeadershipPark edisi VIII]
read more...
Cemas di Tahun Anjing
 Di sebuah milis, seorang kawan mengeluh lantaran dirinya mendapat ramalan yang kurang baik di Tahun Anjing ini. Sepanjang tahun ini, kesehatannya diramal dalam kondisi rapuh, alias rentan penyakit. Ia sendiri sudah mulai merasakan flu dan kesakitan di tangannya. Ia tampak begitu gelisah. Tak heran, jika ia minta didoakan agar lekas sembuh dan tetap hidup dengan kesehatan yang prima.
Di sebuah milis, seorang kawan mengeluh lantaran dirinya mendapat ramalan yang kurang baik di Tahun Anjing ini. Sepanjang tahun ini, kesehatannya diramal dalam kondisi rapuh, alias rentan penyakit. Ia sendiri sudah mulai merasakan flu dan kesakitan di tangannya. Ia tampak begitu gelisah. Tak heran, jika ia minta didoakan agar lekas sembuh dan tetap hidup dengan kesehatan yang prima.
Menjelang dan sesudah Imlek kemarin, beberapa media massa menerbitkan artikel seputar ramalan di Tahun 2006, khususnya peristiwa yang akan terjadi secara nasional di Negeri ini. Banyak ragam ramalan. Dan, banyak orang yang cari-cari ramalan tentang hidupnya masing-masing. Tak pelak, Fengshui, ramalan bintang (zodiak), paranormal, dukun, dan berbagai jenis ‘orang pintar’ diserbu banyak orang. Obrolan tentang ramalan ini pun seru dan ramai terjadi di milis-milis, ruang chatting, obrolan makan siang, dan sebagainya.
Bagiku, fenomena ini sangat menarik. Letak menariknya justru pada orang-orang yang berambisi untuk diramal. Mereka tentu senang dianggap dirinya modern dan bukan orang kuno. Bagaimana orang-orang modern masih mempercayai adanya nasib atau takdir dan melakukan ramal meramal? Realitas ini tidak dapat disangkal. Masih banyak orang yang percaya pada nasib atau garis hidup.
Anthony Giddens, sosiolog asal Inggris, mengatakan bahwa paham nasib memang tidak lekang begitu saja di alam modernitas ini. Keyakinan pada hal-hal gaib, konsep takdir, dan kosmologi, masih saja hidup. Tapi, hal-hal itu, sudah berubah menjadi semacam tahayul, yang setengah dipercaya orang dan diikuti dengan agak malu-malu. Misalnya, para penjudi, para spekulan di pasar saham, masih punya ritual yang secara psikologis mengurangi rasa ketidakpastian dalam hidup. Tak jarang, mereka berkonsultasi pada para astrolog.
Modernitas menyuguhkan beragam ketidakpastian. Takdir adalah sebuah kepastian. Oleh itu itu, takdir atau nasib sudah usang di alam kontemporer ini. Penggantinya adalah konsep risiko. Konsep ini melekat pada masyarakat yang berorientasi ke masa depan. Risiko juga mengacu pada bahaya yang secara aktif diperkirakan dengan kemungkinan yang akan terjadi. Risiko membutuhkan praktek kalkulasi.
Bagiku, bencana tsunami, tanah longsor, flu burung, banjir bandang, jatuh pailit bagi perusahaan, merupakan risiko dan bukan takdir. Bahkan, Giddens menilai risiko di dunia modern adalah buatan manusia sendiri (manufactured risk). Risiko eksternal sudah tergeser oleh risiko buatan. Risiko yang tampaknya eksternal (bencana alam) seperti tanah longsor, banjir, pemanasan global, adalah buatan. Ini terkait dengan perbuatan manusia, seperti pembabatan hutan serampangan, perusakan ekologi, efek rumah kaca, dan sebagainya.
Aku sendiri bukan orang yang mempercayai takdir. Jujur, aku juga senang baca zodiak dan ramalan. Tapi, sekadar iseng-iseng saja. Kalau ramalannya baik, ya senang saja. Kalau buruk, forget it! Aku lebih meyakini bahwa manusia dilahirkan dengan kebebasan. Dia sendiri yang menentukan masa depannya. Justru, hadiah paling agung dari Sang Pencipta untuk manusia adalah kebebasannya.
Kalau ada nasib, untuk apa manusia berdoa dan mohon pertolongan Tuhan? Dan untuk apa manusia bekerja dan berbuat baik? Toh, apa pun yang kita kerjakan, kita akan menemui apa yang sudah tersurat. Bagiku, takdirku hanya ada dua, yakni aku dilahirkan dan menuju kematian. Dalam bahasanya Heidegger sebagai keterlemparan dan ada menuju kematian (Sein zum Tode). Atau seperti yang dikatakan Giovanni Pico Della Mirandola, “Kita dilahirkan untuk menjadi apa yang kita kehendaki.” Nah, tuh...
read more...
Yang Lucu dari Para Filsuf
 Menyusuri dunia para filsuf tidak selamanya membuat diriku berkerut kening. Tak selalu pusing, tapi bisa juga tertawa. Sebut saja Arthur Schopenhauer (1788-1860). Schopenhauer dikenal sebagai filsuf murung. Ia sering ditimpa kegagalan dan kemalangan.
Menyusuri dunia para filsuf tidak selamanya membuat diriku berkerut kening. Tak selalu pusing, tapi bisa juga tertawa. Sebut saja Arthur Schopenhauer (1788-1860). Schopenhauer dikenal sebagai filsuf murung. Ia sering ditimpa kegagalan dan kemalangan.
Suatu ketika, ia diizinkan mengajar di Universitas Berlin. Di sana, filsuf besar Hegel juga mengajar. Karena sombong, ia ingin menyaingi Hegel. Ia menempatkan jam-jam kuliahnya pada jam-jam di mana Hegel juga mengajar. Sayangnya, Schopenhauer kalah peminat. Ia patah semangat dan hengkang dari universitas selamanya.
Ia adalah seorang jomblo sejati, alias selalu gagal dalam pacaran. Tapi, ia adalah orang kaya, tinggal di Frankfurt dan selalu merasa ketakutan. Pistol terisi selalu menjadi teman tidurnya. Di rumah besar lengkap dengan perpustakaan, ia meratap dan menulis. Ia banyak menulis, tapi tulisan tidak laku jual. Agar terkesan laku, ia membeli seluruh oplah bukunya dan menyimpannya.
Shopenhauer hidup sendirian. Ia muak bergaul dengan orang lain. Tambah satu lagi yang lucu darinya, yakni satu-satunya teman setia Schopenhauer adalah seekor anjing putih yang selalu menemaninya jalan-jalan. Pada tahun 1860, ia meninggal akibat sakit paru-paru. Menjelang ajalnya, tulisan-tulisannya baru dikenal dan diedarkan.
Ada sisi lain yang unik dari filsuf-filsuf lain. Karl Marx, filsuf besar yang mempengaruhi dunia ini, harus meninggal dan hanya ditemani oleh delapan sahabatnya saat pemakamannya. Biji gandum memang harus jatuh ke tanah dan mati. Setelah itu, baru tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Nah, delapan orang kawan tadi belum ada artinya dengan jutaan orang-orang yang mengaku dirinya Marxist. 
Ada lagi Thomas Hobbes (1588-1679). Filsuf yang menggaungkan jargon bellum omnium contra omnes (perang semua melawan semua) ini mengaku dilahirkan sebagai bayi prematur di Malmesbury, 25 Km dari London. Ia dilahirkan saat Inggris dalam kondisi ribut dan mengerikan. Oleh karenanya, dengan jujur, ia mengaku, “Ibuku melahirkan dua bayi kembar: aku dan ketakutanku.”
Kabur dari rumah ternyata tidak hanya dialami remaja zaman sekarang, tapi juga Jean-Jaques Rousseau (1712-1778). Pada usia 16 tahun, putra dari tukang arloji ini, minggat dari rumah. Ia menjadi pengembara di perbatasan Swiss-Perancis. Di sini, ia bertemu dengan seorang janda Katolik. Ia menjadi murid, pacar, sekaligus anaknya. Lalu, demi cinta, ia pindah agama dari Kalvinisme ke Katolik. Untung tidak dianggap murtad seperti di Indonesia.
Namanya juga orang Jerman, ia terkenal kaku dan disiplin. Mirip-mirip Franz-Magnis Suseno, maestro filsafat Indonesia. Namanya Immanuel Kant (1724-1804). Dari hari ke hari, hidupnya berjalan monoton dan tertib. Katanya, setiap hari Kant mempunyai acara yang sama. Nah, karena begitu ketatnya acara Kant, sampai-sampai penduduk Konigsberg tahu bahwa hari itu pukul setengah lima sore saat melihat Kant melewati halaman balai kota, lengkap dengan tongkat kayu dan jas kelabunya.
Nah, itu hanya pecahan dari narasi hidup para filsuf. Tentu, masih banyak yang lain. Toh, menjadi filsuf katanya sama saja menjadi orang gila. Enjoy dengan kisah-kisah ini, silakan saja belajar filsafat...filsafat kadang keras, tapi kadang renyah. Kadang bikin pusing, tapi kali-kali bikin senyum mengembang....
read more...
Maria Tanpa Kaki
 Malam telah larut. Beberapa waktu lagi, malam akan runtuh, diganti pagi. Hawa dingin menyapu pelan seluruh tubuh. Sesekali terdengar gonggongan anjing kampung saat perempuan tua itu duduk tersimpuh di atas tikar yang sudah usang dan bolong di sana-sini. Wajahnya yang mulai keriput tampil samar-samar karena pendaran cahaya lilin yang sudah tidak utuh lagi lantaran di makan api. Sementara itu, tangannya yang sudah tidak sekuat dulu, memilin pelan satu persatu butir rosario. Rosario yang terbuat dari kayu cendana dan menebar bau wangi itu digenggamnya erat. Seolah tidak ingin ia lepaskan demi sebuah pengharapan yang tiada habis.
Malam telah larut. Beberapa waktu lagi, malam akan runtuh, diganti pagi. Hawa dingin menyapu pelan seluruh tubuh. Sesekali terdengar gonggongan anjing kampung saat perempuan tua itu duduk tersimpuh di atas tikar yang sudah usang dan bolong di sana-sini. Wajahnya yang mulai keriput tampil samar-samar karena pendaran cahaya lilin yang sudah tidak utuh lagi lantaran di makan api. Sementara itu, tangannya yang sudah tidak sekuat dulu, memilin pelan satu persatu butir rosario. Rosario yang terbuat dari kayu cendana dan menebar bau wangi itu digenggamnya erat. Seolah tidak ingin ia lepaskan demi sebuah pengharapan yang tiada habis.
Perempuan tua itu bernama Sumijati. Nama permandiannya, Veronica. Di depan perempuan yang akrab dipanggil mbak Sum itu, ada sebuah patung Maria yang sudah tidak utuh lagi berdiri condong di atas meja. Patung itu pemberian anak laki-lakinya 10 tahun silam saat ia berada di seminari dan ia beli saat berziarah ke Sendang Sono. Badan patung Maria telah patah dan pecah sehingga bagian kaki yang menginjak ular sudah tidak ada lagi. Konon, katanya, patung itu pernah jatuh dari almari. Tapi, mbak Sum tidak mau membuang dan menggantinya dengan yang baru. Anak perempuannya yang kini tinggal di Jakarta karena ikut suami, membelikannya patung Maria yang utuh, ukurannya lebih besar, dan menarik. Tapi, mbak Sum tetap berdoa dengan patung Maria yang sudah tidak ada kakinya itu.
Mbak Sum sangat mencintai patung Maria tanpa kaki. Keduanya seperti sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Mereka sudah saling menyatu. Suatu siang, aku pernah menanyakan hal ini. “Ibu, kenapa ibu tetap memakai patung yang sudah pecah itu? Bukannya kakak sudah membelikannya yang baru,” kataku. Dengan sangat sederhana, ibu itu menjawab, “Patung itu sungguh mau mendengarkan ibu!” Mendengar ini, aku belum mengerti apa yang dimaksud ibu itu. Aku sengaja tidak melanjutkan pertanyaanku. Aku rasa saat itu ibu memang begitu mencintai patung itu karena kedekatan emosi. Lumrah, sama seperti ketika aku juga tidak lepas dari t-shirt yang selalu aku kenakan karena ada ikatan emosi dan cerita di balik t-shirt itu. Orang lain pun pasti punya pengalaman serupa. Entah dengan surat, sapu tangan, cincin, dan sebagainya.
Tapi, malam yang hampir runtuh dan akan diganti pagi itu telah membukakan mata hatiku. Lilin yang hampir habis karena lumer itu masih memberikan beberapa cercah cahaya sehingga aku bisa memandangi patung Maria itu dengan saksama. Sementara, mulut mbak Sum terus mengucapkan “Sembah Bekti Kawula Dewi Maria” atau doa Salam Maria.
Tiba-tiba, ada sesuatu pemandangan yang unik dan indah terjadi di malam itu. Pemandangan yang tidak pernah aku jumpai selama hidup. Patung Maria tanpa kaki itu terlihat condong. Patung Maria itu tidak lagi berdiri dengan kakinya, tetapi harus disangga dengan sebuah vas bunga kecil. Karena tidak imbang, maka patung itu condong atau miring. Namun, justru karena miring inilah, patung itu tampak sungguh-sungguh mendengarkan perempuan yang sedang berdoa itu. Aku baru sadar apa yang dikatakan mbak Sum siang itu: “Patung itu sungguh mau mendengarkan ibu!”
Dan lihat, keduanya seperti tampak begitu erat. Pemandangan yang menakjubkan. Meski tanpa kaki, Maria itu tampak cantik sekali, sangat anggun, penuh keibuan dan siap mendengarkan apa saja yang mau dikatakan mbak Sum. Maria juga seolah siap menumpahkan seluruh rahmat dan cintanya untuk mbak Sum. Maria benar-benar diimani sebagai pribadi yang sungguh mendengar dan menjadi sang pengantara rahmat. Mbak Sum telah menemukan telaga rohani yang tiada habis digali. Telaga yang tidak pernah kering lantaran musim kemarau. Telaga yang selalu memberikan pengharapan dalam segala ketidakpastian dan kemustahilan dunia. Maria tanpa kaki itu menjadi tempat mbak Sum bercurhat secara intim dengan ibundanya. Mungkin, Maria tanpa kaki inilah yang selama ini menguatkan iman mbak Sum dalam menghadapi berbagai cobaan hidup yang sedang ia hadapi. Lebih-lebih, menghadapi dan menggeluti persoalan yang menimpa anak bungsunya yang terjerat narkoba yang sampai kini belum sembuh benar.
Maria tanpa kaki, itulah wujud nyata iman mbak Sum yang tak lain adalah ibu kandungku sendiri. Maria yang selalu mencondongkan diri pada setiap orang untuk mendengarkan yang berbisik padanya dalam doa...
* Saat menemukan celah keheningan di tembok kebisingan Jakarta...
[tulisan ini pernah dimuat di Majalah Utusan, terbitan Kanisius]
read more...
Stiker Militer
 Perjalanan menuju kantor pagi ini (16/1) diwarnai dengan beragam pemandangan. Jalanan sepanjang Rawa Belong-Palmerah cukup padat. Mikrolet M-11 berjejal dan beradu dengan kendaraan lain. Sepeda motor yang kunaiki pun tidak bisa berjalan cepat, pelan, dan harap sabar. Untuk mengatasi kesumpekan pagi itu, mataku lumayan kreatif untuk memandangi kendaraan di depanku atau melintas di jalur seberang.
Perjalanan menuju kantor pagi ini (16/1) diwarnai dengan beragam pemandangan. Jalanan sepanjang Rawa Belong-Palmerah cukup padat. Mikrolet M-11 berjejal dan beradu dengan kendaraan lain. Sepeda motor yang kunaiki pun tidak bisa berjalan cepat, pelan, dan harap sabar. Untuk mengatasi kesumpekan pagi itu, mataku lumayan kreatif untuk memandangi kendaraan di depanku atau melintas di jalur seberang.
Selain membaca tulisan beragam di kaca belakang tiap mikrolet, mataku juga melihat beragam stiker yang tertempel di mobil-mobil itu. Hampir tiap hari, aku melihat stiker warna kuning bertuliskan “Taman Safari” dengan bentuk badak atau singa tertempel di kaca belakang mobil. Namun, beberapa kali, aku juga melihat stiker berwarna hijau, kadang doreng (hijau-coklat) bertuliskan “Angkatan Darat”, “Keluarga Mabes TNI”, atau “PM” (Polisi Militer) tertempel di kaca mobil atau bodi sepeda motor. Anehnya, pengemudi mobil atau motor itu berperawakan bukan sebagai seorang anggota militer atau polisi. Bisa jadi, memang keluarga dari militer atau polisi.
Aku teringat pada omku saat liburan di Jogja. Saat berpergian dengannya, omku menghentikan balenonya untuk membeli stiker militer bertulis “keluarga besar TNI”. Katanya, biar aman. Aku bertanya, aman dari apa? Dari orang jahat atau polisi lalu lintas? Padahal, dia bukan keluarga besar TNI. Apakah dengan stiker itu, mobil itu bisa aman dari orang jahat dan kebal dari aturan lalu lintas?
Ah, bagiku kenapa harus takut? Kenapa berlindung di balik stiker? Bukan kebanggaan memakai stiker itu, melainkan ketakutan di balik plastik lengket itu. Toh, ketakutan hanya melahirkan berbagai kepura-puraan. Tapi, ini fenomena konkret di depan mata. Aku pun pernah mau memasang stiker itu.
Pendekar Miyamoto Musashi dalam novelnya Eiji Yoshikawa pernah berujar, “Aku tidak takut pada siapa pun. Satu yang aku takuti, yakni ketakutan itu sendiri.” Pendekar pedang asal Negeri Sakura itu menyadari ketakutan adalah potensi awal sebuah kekalahan. So, mengapa takut?
read more...
Mimpi Belajar di London
 Boleh dong aku mempunyai mimpi. Mimpi adalah salah satu yang tidak bisa dibelenggu dengan rantai mana pun, termasuk undang-undang. London adalah mimpiku. Melihat London secara langsung atau belajar di Negerinya Harry Potter itu. Dorongan pergi ke London bukan sekadar dorongan untuk jalan-jalan saja. Tapi, belajar. Boleh dong mengejawantahkan makna pepatah “belajarlah sampai Negeri Cina.” Maksudnya, belajar sekuat tenaga dan sebanyak mungkin.
Boleh dong aku mempunyai mimpi. Mimpi adalah salah satu yang tidak bisa dibelenggu dengan rantai mana pun, termasuk undang-undang. London adalah mimpiku. Melihat London secara langsung atau belajar di Negerinya Harry Potter itu. Dorongan pergi ke London bukan sekadar dorongan untuk jalan-jalan saja. Tapi, belajar. Boleh dong mengejawantahkan makna pepatah “belajarlah sampai Negeri Cina.” Maksudnya, belajar sekuat tenaga dan sebanyak mungkin.
Perjumpaan dengan kawan yang studi di sana membangkitkan mimpiku. Hari Juliawan, seorang Jesuit muda, kakak angkatanku dulu, sudah menyelesaikan studinya di University of Warwich dengan gemilang. Sekarang, ia mendapat tugas belajar di Oxford University. London menjadi salah satu alternatif untuk belajar.
Menarik memang menggeluti dunia akademis. Pengetahuan yang dipelajari menjadi jendela memahami dunia. Filsafat, budaya, sosiologi, politik, globalisasi adalah topik-topik yang menarik untuk digeluti.
Apakah ini bukan sekadar khayalan kosong? Tidak, kataku. I have a dream, sependapat dengan anak muda West Life. Memang, ke sana butuh banyak biaya. Tapi, biaya tidak menghalangi proses mewujudkan mimpi. Aku sendiri orang yang menyakini apa yang dikatakan Paulo Coelho dalam novelnya “The Alchemist.” Khususnya, tentang pencapaian mimpi dan cita-cita personal. Tiap orang mempunyai Legenda Pribadi. Legenda ini akan terwujud kalau orang dengan yakin dan kehendak kuat mau mewujudkannya. Tidak ada nasib, tidak ada takdir. Persis juga seperti yang dikatakan teroris yang mengebom Gedung Federal Oklahoma, Timothy McVeigh, “I am the master of my Fate.”
Mau tidak mau, hal fundamental yang harus kukuasai adalah bahasa Inggris. Noni, sahabatku lewat telepon, menyarakan aku untuk kursus bahasa Inggris saja. Tidak hanya belajar sendiri. Alasannya, dengan kursus ada pemicu dan ‘paksaan’ yang memajukan.
Nah, itu yang ada dalam benakku sekarang. Burung masih punya sayap untuk terbang. Aku masih mimpi untuk bisa belajar lagi. London, laksana sebuah Tanah Terjanji...
Bermil-mil kilometer, sudah aku rasakan tiupan hawa dingin dan serpihan salju putih mengelus kulitku yang item. Sembari memandangi jendela kamarku, melihat ke bawah ke arah lampu kota, dan seorang kawan membacakan kisah CS. Lewis berjudul The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe. Atau, di sebuah liburan, aku mewawancari langsung JK. Rowling, sang pengarang Harry Potter....
London oh London...
read more...
















